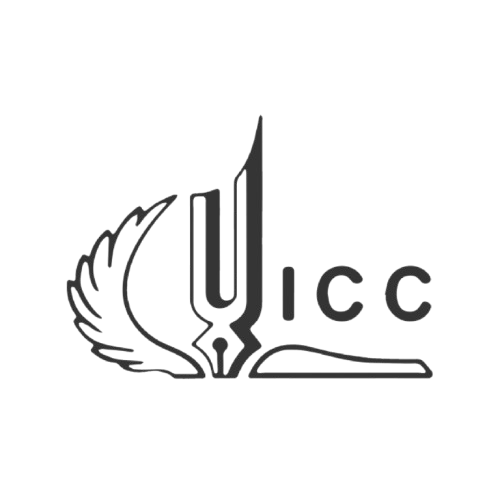NGOBRAS (Ngobrolin Agama dan Sains) Seri ke-3 berlangsung pada Jumat, 24 Oktober 2025 di Aula Imam Khomeini, ICC Jakarta. Acara yang mengangkat tema “Apakah AI Bisa Mencalonkan Diri Sebagai Presiden 2029?” ini menghadirkan dua narasumber untuk membedah persoalan kesadaran dan hak politik kecerdasan buatan dari sudut pandang sains dan spiritualitas. Salah satu narasumber, Budi Sulistyo, penulis buku Apakah Silikon Bisa Menangis? sekaligus praktisi kecerdasan buatan, menjelaskan tentang hakikat kesadaran dan kecerdasan buatan dalam konteks perkembangan teknologi dan filsafat manusia.
Budi Sulistyo membuka penjelasannya dengan menguraikan perbedaan mendasar antara kecerdasan manusia dan kecerdasan buatan. Menurutnya, yang membedakan manusia dari sistem kecerdasan buatan adalah kesadaran. Manusia bukan hanya cerdas, tetapi juga sadar. Ia kemudian mengulas sejarah perkembangan gagasan kecerdasan buatan yang dimulai dari pemikiran Alan Turing pada pertengahan abad ke-20. Turing merumuskan konsep mesin yang mampu menjalankan fungsi-fungsi logis dan matematis sebagaimana manusia berpikir. Melalui apa yang kemudian dikenal sebagai Turing Test, ia mengajukan pertanyaan apakah komputer dapat dianggap cerdas jika mampu bercakap-cakap dengan manusia tanpa bisa dibedakan.
Perkembangan selanjutnya, kata Budi, ditandai dengan penemuan transistor yang meningkatkan kemampuan komputer, serta munculnya program awal seperti ELIZA yang sudah bisa berinteraksi secara sederhana dengan manusia. Pada dekade 1980-an, berkembang pula konsep neural network yang meniru cara kerja otak manusia, menjadi dasar bagi teknologi kecerdasan buatan modern.
Budi menjelaskan bahwa kecerdasan buatan secara umum terbagi menjadi dua kategori. Pertama, narrow AI atau kecerdasan buatan sempit, yaitu sistem yang dirancang untuk fungsi tertentu seperti sistem pengereman otomatis pada kendaraan. Kedua, general AI, kecerdasan yang digadang-gadang dapat menyamai kapasitas kognitif manusia. Dalam konteks ini, large language model menjadi salah satu bentuk penerapan yang paling populer, dengan kemampuan memproses dan menghasilkan bahasa berdasarkan analisis terhadap jutaan kata.
Selain itu, kini telah berkembang pula multimodal AI yang mampu mengenali dan menghasilkan gambar, serta agentic AI yang bersifat otonom dan dapat mengambil keputusan secara mandiri, misalnya dalam pengoperasian kendaraan atau sistem pabrik. Namun, di balik semua kemampuan itu, Budi menekankan bahwa perbedaan mendasar antara manusia dan mesin tetap terletak pada adanya subjek yang sadar.
Ia menguraikan konsep tentang “homunculus” atau keberadaan subjek yang memandang dirinya sendiri. Dalam pandangan filsafat klasik seperti René Descartes, subjek manusia bersifat immaterial dan rasional. Namun dalam kajian sains modern, kapasitas rasional itu erat kaitannya dengan fungsi otak. Jika otak mengalami kerusakan, maka fungsi kognitif juga menurun. Karena itu, kesadaran tidak bisa sepenuhnya dipisahkan dari kondisi material tubuh manusia.
Meski demikian, manifestasi kesadaran tidak bisa direduksi semata-mata sebagai proses material. Aktivitas berpikir yang bersifat immaterial selalu termanifestasi melalui medium material, seperti kerja otak dan sistem saraf. Dalam konteks ini, pengalaman sadar hanya mungkin terjadi jika ada subjek yang hidup dan memiliki hubungan langsung dengan tubuhnya.
Budi kemudian menegaskan bahwa kesadaran memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan. Pertanyaan apakah kecerdasan buatan dapat memiliki kesadaran harus diawali dengan pertanyaan apakah kecerdasan buatan dapat hidup. Kehidupan ditandai dengan dinamika sistemik yang terus berlangsung dan berinteraksi dengan lingkungan. Jika dinamika ini terhenti, maka kesatuan subjek juga lenyap — yang berarti kematian.
Kesadaran, menurutnya, juga melahirkan kemampuan memilih secara bebas (free will). Manusia memang memiliki sebab dan latar belakang tertentu dalam bertindak, namun tetap dapat memilih secara indeterministik. Organisme yang lebih kompleks justru menunjukkan tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi, karena tidak seluruh tindakannya ditentukan oleh sebab akibat yang pasti.
Kecerdasan buatan bisa meniru sebagian sifat indeterministik ini melalui algoritma acak, tetapi sifat acaknya bersifat palsu karena masih bergantung pada struktur yang telah diprogram. Sementara indeterminasi manusia memiliki makna dan arah tindakan yang jelas, bukan semata-mata hasil acak.
Budi juga menekankan bahwa kesadaran manusia bersifat embodied, yakni tersebar di seluruh tubuh, bukan hanya di otak. Ia mencontohkan fenomena muscle memory pada aktivitas fisik seperti bermain musik atau berolahraga, di mana tubuh turut menyimpan dan mengekspresikan bentuk pengetahuan tertentu.
Dengan demikian, kesadaran tidak sekadar kemampuan berpikir, melainkan kesatuan antara tubuh, kehidupan, dan pengalaman subjektif. Melalui paparan Budi Sulistyo, peserta diajak memahami bahwa meskipun kecerdasan buatan telah berkembang sangat jauh, hakikat kesadaran tetap menjadi wilayah yang unik bagi manusia — sesuatu yang belum dapat dijangkau oleh algoritma, secerdas apa pun sistem yang diciptakan.