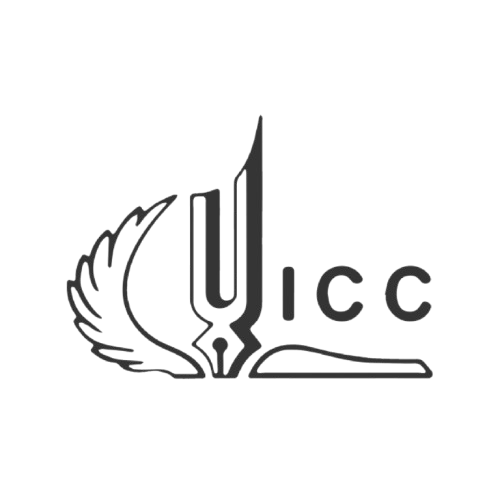NGOBRAS (Ngobrolin Agama dan Sains) Seri ke-3 berlangsung pada Jumat, 24 Oktober 2025 di Aula Imam Khomeini, ICC Jakarta. Forum yang mengangkat tema “Apakah AI Bisa Mencalonkan Diri Sebagai Presiden 2029?” ini mempertemukan dua narasumber untuk menelaah persoalan kecerdasan buatan dari sudut pandang ilmu pengetahuan dan spiritualitas. Setelah sebelumnya peserta mendengarkan penjelasan mendasar tentang kesadaran dan kecerdasan dari sisi sains modern, sesi berikutnya diisi oleh Sayyid Hasan Shahab, Ketua Asosiasi Data Sains dan AI Indonesia, yang mengulas kecerdasan buatan melalui perspektif filsafat Islam klasik.
Sayyid Hasan Shahab mengawali pemaparannya dengan menyebut bahwa apa yang disampaikan sebelumnya telah memberikan fondasi ilmiah tentang kecerdasan dan kesadaran dari pandangan modern. Ia kemudian mengajak peserta untuk melihat tema tersebut dari sudut pandang para filsuf Muslim, khususnya pemikiran Ibn Sina. Menurutnya, gagasan Ibn Sina masih sangat relevan untuk memahami persoalan hakikat kecerdasan dan kehidupan dalam konteks kemajuan teknologi masa kini.
Sebagai contoh fenomena aktual, ia menyinggung keputusan pemerintah Albania yang baru-baru ini mengangkat Diella, sebuah sistem kecerdasan buatan, sebagai Menteri Pemberantasan Korupsi. Jika kecerdasan buatan dapat menduduki jabatan seperti itu, secara logika muncul pertanyaan apakah kelak AI juga bisa mencalonkan diri sebagai presiden. Dalam konteks kinerja administratif, keunggulan AI terletak pada kemampuannya bekerja tanpa batas waktu, memproses data dalam jumlah besar, serta meminimalkan bias dan subjektivitas manusia. Dengan algoritma yang tepat, AI bahkan dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam birokrasi.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pertanyaan mendasarnya bukan hanya pada efektivitas teknis, melainkan pada batas-batas kemanusiaan. Manusia bukan sekadar makhluk yang berjalan berdasarkan data dan algoritma. Ada dimensi kreativitas, kebaruan, tanggung jawab moral, dan konteks sosial-politik yang tidak bisa direduksi menjadi perhitungan logis. Keputusan-keputusan publik, terutama di ranah politik, sering kali melibatkan pertimbangan etika dan nilai-nilai moral yang tidak bisa ditentukan oleh data. Selain itu, jika suatu sistem AI diretas atau dimanipulasi oleh pihak lain, tanggung jawab atas dampaknya menjadi masalah serius yang belum memiliki jawaban tuntas.
Dari persoalan ini, Sayyid Hasan Shahab kemudian mengarahkan pembahasan pada dimensi ontologis AI. Ia menjelaskan bahwa kemajuan teknologi kecerdasan buatan tidak hanya menyangkut cara kerja, tetapi juga hakikat keberadaannya. Dalam sains sendiri, istilah “kecerdasan” dan “pikiran” masih menyimpan ambiguitas, padahal keduanya memiliki implikasi yang mendalam terhadap bobot moral dan keagamaan.
Ia mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai bidang ilmu yang berupaya membuat sistem yang berpikir, belajar, dan berperilaku menyerupai kecerdasan manusia. Pendekatan terhadap AI dapat berbeda-beda tergantung disiplin ilmunya, tetapi semuanya berpusat pada upaya meniru kapasitas kognitif manusia. Jika dahulu teknologi dianggap sebagai penerapan sains, kini melalui AI batas antara keduanya menjadi kabur karena sains sendiri bergerak melalui kemampuan kognitif yang ditiru dari manusia.
Secara umum, AI dibangun atas tiga unsur utama, yaitu unit pemrosesan, algoritma, dan data. Karena memiliki perilaku dan proses belajar, AI kemudian menjadi bidang kajian lintas disiplin: dari sains dan teknologi, ilmu saraf, hingga psikologi dan filsafat. Dalam konteks ini, Sayyid Hasan Shahab menjelaskan relevansi Ibn Sina sebagai tokoh multidisipliner yang memiliki sistem filsafat komprehensif tentang realitas, jiwa, dan pengetahuan. Kerangka kerja Ibn Sina, menurutnya, memberi landasan kuat bagi definisi berpikir dan kesadaran yang dapat digunakan untuk menganalisis fenomena kecerdasan buatan.
Ia merujuk pada karya What Philosopher Ibn Sina Can Teach Us About AI yang menyoroti bagaimana pemikiran Ibn Sina menjadi relevan kembali untuk memahami AI masa kini. Ibn Sina membedakan antara esensi dan eksistensi, kausalitas dan substansi, serta membagi keberadaan menjadi wujud natural dan artifisial. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada sumber gerak: yang natural memiliki sumber gerak dari dalam dirinya sendiri, sedangkan yang artifisial bergerak karena intervensi luar.
Dari sini, AI dipahami sebagai sesuatu yang artifisial. Geraknya bergantung pada manusia dan tidak memiliki tujuan internal. Dalam kerangka Ibn Sina, sesuatu yang artifisial termasuk dalam kategori aksiden, bukan substansi. Yang bersifat natural bersatu dengan tujuannya, sedangkan yang artifisial hanya manipulasi simbolik tanpa ruh yang menggerakkan.
Sayyid Hasan Shahab menjelaskan lebih lanjut bahwa manusia, ketika menciptakan benda-benda artifisial, hanya dapat membentuk fungsi dan bentuknya, bukan substansinya. Sebuah kursi misalnya, tetap disebut kursi meskipun dibuat dari bahan yang berbeda karena fungsinya tidak berubah. Namun sesuatu yang natural, seperti makhluk hidup, memiliki substansi yang menentukan identitasnya. Perubahan pada substansi mengubah hakikatnya.
Dalam kerangka ini, AI tidak memiliki jiwa atau kesadaran diri sebagaimana makhluk hidup. Ia hanya merefleksikan struktur simbolik dan algoritmik yang dibangun oleh manusia. Kreativitas yang muncul dari AI hanyalah hasil kombinasi, bukan imajinasi sejati yang melahirkan kebaruan dari pengalaman spiritual dan intelektual.
Sayyid Hasan Shahab mengutip pandangan dari The Creativity Code: How AI is Learning to Write, Paint and Think karya Marcus du Sautoy, yang membedakan antara explanatory creativity dan transformative creativity. Kecerdasan buatan mungkin mampu melakukan kreativitas penjelasan, tetapi tidak bisa mencapai kreativitas transformatif yang mencipta makna baru di luar data yang ada.
Dalam pandangan Ibn Sina, persepsi manusia dimulai dari indera yang mengumpulkan data empiris, kemudian diolah menjadi imajinasi dan disimpan dalam memori. Dari sana lahir makna dan abstraksi yang melibatkan jiwa. Proses ini menegaskan bahwa berpikir sejati tidak berhenti pada otak, tetapi berhubungan dengan dimensi ruhani.
Kesimpulan yang ditarik Sayyid Hasan Shahab adalah bahwa kecerdasan buatan secara ontologis tetap bersifat aksidental dan bergantung pada perangkat keras yang menjadi substansinya. Algoritma yang menopangnya bergantung pada manusia, dan sumber datanya berasal dari kesadaran manusia sendiri. Oleh karena itu, AI tidak bisa menjadi entitas otonom yang berdiri sendiri, apalagi menjadi pemimpin atau presiden.
Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa teknologi tidak pernah netral. Karena itu, pengembangan kecerdasan buatan harus disertai dengan etika, regulasi, dan pemahaman yang matang. AI hanya bisa menjadi alat bantu yang baik bagi manusia, bukan pengganti kesadaran dan tanggung jawab moral manusia itu sendiri.