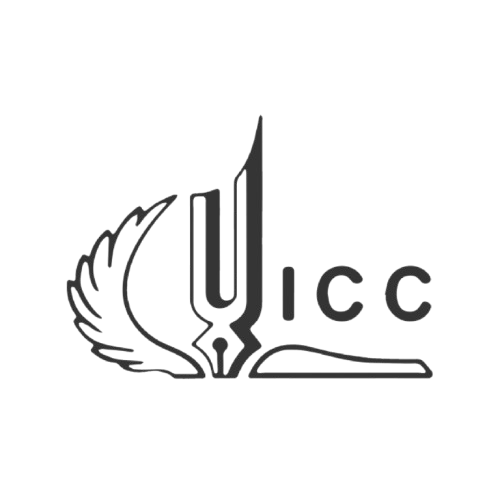Kelas Tafsir Tartibi ICC Jakarta pada Jumat, 7 November 2025, bersama Ustaz Umar Shahab masih melanjutkan kajian tafsir Surah Al-Baqarah. Pada kesempatan tersebut, pembahasan difokuskan pada ayat-ayat yang berkaitan dengan kaum Yahudi, mulai dari ayat ke-40 dan seterusnya. Namun sebelum itu, Ustaz Umar terlebih dahulu memberikan penjelasan tambahan dari kajian pekan sebelumnya yang membahas tentang pengangkatan manusia sebagai khalifah di muka bumi.
Beliau menjelaskan kembali ayat 37 yang berbunyi fa talaqqâ âdamu mir rabbihî kalimâtin fa tâba ‘alaîh, innahû huwat-tawwâbur-raḥîm, yang artinya “Kemudian, Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu Dia pun menerima tobatnya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.” Menurut Ustaz Umar, ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Adam a.s. menyesali perbuatannya mendekati pohon khuldi, sehingga beliau memohon ampun kepada Allah swt dan Allah pun mengampuninya. Kalimat-kalimat yang diterima Nabi Adam a.s. dari Allah adalah doa yang kemudian beliau panjatkan: Rabbana zhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khâsirîn, “Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi.”
Dari sini muncul pertanyaan, apakah Nabi Adam a.s. termasuk orang yang berdosa? Ustaz Umar menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pandangan antara Syiah dan Ahlusunnah mengenai kemaksuman para nabi. Dalam pandangan Syiah, seluruh nabi dan rasul adalah maksum, yaitu terjaga dari dosa sejak awal karena kedudukan mereka sebagai pembawa risalah dan teladan bagi umat manusia. Sedangkan di kalangan Ahlusunnah, terdapat dua pandangan. Pertama, para nabi juga maksum, namun dalam artian mereka mungkin melakukan dosa tetapi Allah segera mengingatkan dan mengampuninya. Pandangan kedua menyatakan bahwa nabi juga bisa melakukan kesalahan karena mereka tetap manusia biasa.
Menurut pandangan Syiah, seorang nabi tidak mungkin berbuat dosa, karena hal itu bertentangan dengan statusnya sebagai penyampai risalah Allah swt. Nabi adalah kepercayaan Allah untuk menjelaskan ajaran-Nya dan menjadi teladan bagi umat. Jika nabi melakukan kesalahan dalam menyampaikan wahyu atau menafsirkan kehendak Allah, maka umatnya akan jatuh dalam kesesatan. Oleh sebab itu, kemaksuman merupakan konsekuensi logis dari misi kenabian. Di kalangan Ahlusunnah, kemaksuman nabi dipahami sebagai penjagaan dari kesalahan melalui teguran Allah, seperti yang terdapat dalam beberapa ayat yang “menegur” Nabi Muhammad saw, misalnya dalam Surah At-Tahrim. Adapun pandangan yang membolehkan nabi berbuat salah ditolak oleh Syiah dengan alasan bahwa potensi berbuat salah memang ada pada manusia, tetapi tidak mungkin terwujud pada para nabi karena bimbingan langsung dari Allah swt.
Sebagai contoh, Ustaz Umar mengutip kisah Nabi Yusuf a.s. dalam Al-Qur’an ketika digoda oleh Zulaikha. Allah berfirman: wa laqad hammat bihî wa hamma bihâ lau lâ an ra’â burhâna rabbih, kadzâlika linashrifa ‘an-hus-sû’a wal-fahsyâ’, innahû min ‘ibâdinal-mukhlashîn, “Sungguh, perempuan itu benar-benar telah berkehendak kepadanya (Yusuf). Yusuf pun berkehendak kepadanya sekiranya dia tidak melihat tanda (dari) Tuhannya. Demikianlah, Kami memalingkan darinya keburukan dan kekejian. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba Kami yang terpilih.” (QS. Yusuf [12]: 24). Menurut beliau, ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Yusuf a.s. memiliki potensi sebagai manusia untuk tergoda, tetapi tidak terjerumus karena bimbingan langsung dari Allah swt yang memalingkan dirinya dari keburukan.
Demikian pula dengan Nabi Muhammad saw. Allah swt berfirman: wa mâ yanthiqu ‘anil hawâ, in huwa illâ wahyun yûḥâ, “Dan tidaklah ia (Muhammad) berbicara menurut hawa nafsunya. Ucapannya tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).” (QS. An-Najm [53]: 3–4). Wahyu yang dimaksud di sini tidak hanya berupa kalimat, tetapi juga bimbingan ilahi dalam seluruh tindakan dan keputusan Nabi. Karena itu, manusia yang senantiasa dibimbing oleh Allah tidak akan berbuat kesalahan. Nabi menjadi maksum melalui dua hal: pertama, usaha pribadi dalam mengendalikan diri dan menempuh kesempurnaan spiritual; kedua, intervensi langsung dari Allah yang menjaga mereka dari kesalahan. Prinsip ini juga menjadi pelajaran bagi manusia, bahwa usaha harus dimulai dari diri sendiri sebelum mendapat pertolongan dan bimbingan dari Allah.
Kembali kepada kisah Nabi Adam a.s., Allah swt berfirman: qulnâhbiṭû minhâ jamî‘â, fa immâ ya’tiyannakum minnî hudan fa man tabi‘a hudâya fa lâ khaufun ‘alaihim wa lâ hum yaḥzanûn, “Kami berfirman, ‘Turunlah kamu semua dari surga! Lalu, jika datang petunjuk-Ku kepadamu, maka siapa saja yang mengikuti petunjuk-Ku, tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka tidak bersedih hati.’” (QS. Al-Baqarah [2]: 38). Dalam hal ini, ketika disebut bahwa Nabi Adam a.s. “menzalimi diri sendiri”, bukan berarti beliau melakukan dosa dalam arti pelanggaran terhadap larangan yang wajib, tetapi lebih kepada meninggalkan sesuatu yang lebih utama.
Ustaz Umar menjelaskan bahwa dalam pandangan teologis, ada tiga kategori seseorang disebut berdosa. Pertama, ketika melanggar perintah wajib atau larangan yang bersifat mutlak; inilah dosa dalam arti sebenarnya. Kedua, ketika melanggar larangan yang tidak bersifat mengikat atau melakukan hal yang makruh. Perbuatan seperti ini tidak digolongkan sebagai dosa, tetapi tetap termasuk menzalimi diri karena meninggalkan keutamaan. Ketiga, seseorang merasa kurang sempurna dalam penghambaan kepada Allah. Nabi Muhammad saw, meskipun maksum, tetap senantiasa beristighfar kepada Allah hingga tujuh puluh kali setiap beranjak dari suatu tempat. Dalam satu riwayat, Aisyah melihat Nabi menangis pada malam hari sambil beristighfar, lalu bertanya apa kesalahan beliau sehingga memohon ampun sedemikian rupa. Nabi menjawab bahwa beliau tidak berbuat dosa, namun ingin menjadi hamba yang bersyukur. Ini menunjukkan bahwa istighfar Nabi bukan karena dosa, melainkan sebagai bentuk kesadaran akan keterbatasan manusia di hadapan kesempurnaan Allah.
Dengan demikian, ‘kesalahan’ Nabi Adam a.s. atau para nabi lainnya bukanlah kesalahan dalam arti pelanggaran syariat, tetapi meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Hal ini memiliki konsekuensi, tetapi bukan hukuman, melainkan bentuk pendidikan ilahi.
Setelah menjelaskan bagian itu, Ustaz Umar melanjutkan kepada ayat 40 Surah Al-Baqarah yang mulai berbicara tentang Bani Israil. Allah berfirman: Yâ banî isrâ’îl udzkurû ni‘matiyallatî an‘amtu ‘alaikum wa aufû bi‘ahdî ûfi bi‘ahdikum wa iyyâya farhabûn, “Wahai Bani Israil, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu. Hanya kepada-Ku hendaknya kamu takut.” (QS. Al-Baqarah [2]: 40).
Beliau menjelaskan bahwa ayat ini merupakan seruan langsung Allah kepada Bani Israil. Menurutnya, di antara seluruh umat para nabi, kaum Bani Israil mendapat perhatian yang sangat besar dari Al-Qur’an karena dari 25 nabi yang disebutkan di dalamnya, mayoritas berasal dari Bani Israil. Hal ini menunjukkan bahwa umat ini memiliki sejarah panjang dalam menerima wahyu, tetapi juga dalam menolak dan menyimpang dari ajaran para nabi mereka. Karena itu, Allah menegur mereka berulang kali agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Allah mengingatkan mereka tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada nenek moyang mereka. Dalam ayat 49 disebutkan: wa idz najjainâkum min âli fir‘auna yasûmûnakum sû’al-‘adzâbi yudzabbiḥûna abnâ’akum wa yastaḥyûna nisâ’akum wa fî dzâlikum balâ’un mir rabbikum ‘azhîm, “(Ingatlah) ketika Kami menyelamatkan kamu dari (Fir‘aun dan) pengikut-pengikutnya. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu, menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu terdapat cobaan yang sangat besar dari Tuhanmu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 49).
Ustaz Umar menegaskan bahwa nikmat yang dimaksud bukanlah nikmat yang diberikan kepada Bani Israil di masa Nabi Muhammad saw, melainkan kepada nenek moyang mereka. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku negatif orang-orang terdahulu diwariskan oleh generasi berikutnya. Karena itu, Al-Qur’an menyebut kembali kisah mereka agar umat kemudian memahami akar kesalahan yang sama.
Allah juga mengingatkan bagaimana Bani Israil menyembah patung anak sapi setelah Nabi Musa a.s. pergi bermunajat selama empat puluh malam, sebagaimana disebutkan dalam ayat 51: wa idz wâ‘adnâ mûsâ arba‘îna lailatan tsumma-ttakhadztumul-‘ijla mim ba‘dihî wa antum zhâlimûn, “(Ingatlah) ketika Kami menjanjikan kepada Musa (petunjuk Taurat) selama empat puluh malam. Kemudian kamu menjadikan (patung) anak sapi (sebagai sembahan) setelahnya, dan kamu termasuk orang-orang zalim.” (QS. Al-Baqarah [2]: 51).
Ustaz Umar menjelaskan bahwa ayat ini menjadi indikasi bagaimana kaum Yahudi gemar mengubah ajaran para nabi mereka hingga akhirnya menyimpang ke arah penyembahan berhala. Sifat dan kebiasaan tersebut, kata beliau, terus diwariskan hingga kini. Meski ada orang-orang Yahudi yang bersikap baik, secara umum Al-Qur’an menggambarkan kecenderungan kolektif mereka sebagai kaum yang suka menyelewengkan wahyu dan melawan kebenaran.
Beliau kemudian menyinggung keadaan Israel masa kini. Menurutnya, bila kita melihat realitas masyarakat Israel — baik penguasa, oposisi, pebisnis, akademisi, jurnalis, maupun rakyat biasa — hampir seluruhnya menunjukkan sikap yang sama ketika menyangkut urusan Palestina. Inilah sebabnya mengapa Al-Qur’an memberikan perhatian begitu besar kepada kaum Yahudi, karena akan selalu ada hubungan historis dan ideologis antara karakter yang dikritik dalam Al-Qur’an dengan perilaku kaum mereka di masa kini.