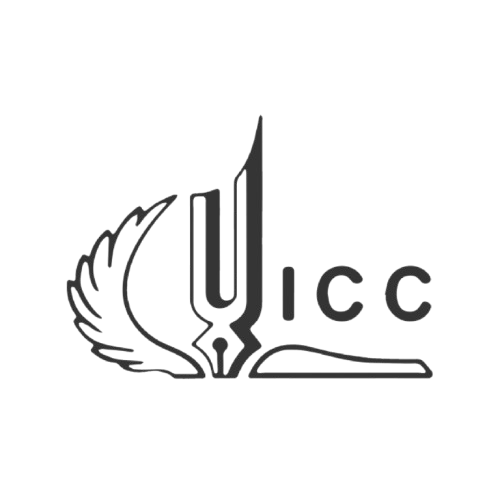Pendahuluan:
Persoalan Wilayatul Faqih (Otoritas Faqih) tidak dapat dibahas tanpa merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang menjadi sumber legitimasi bagi konsep ini, yang mewajibkan semua orang untuk mematuhi perintahnya dan bekerja di bawah panjinya. Hal ini karena Wilayatul Faqih berkaitan dengan serangkaian kewenangan (wilayah) yang bersifat hierarkis hingga akhirnya berujung pada wilayah Allah Yang Mahatinggi. Dari sini, pembahasan ini akan disampaikan dalam dua aspek:
● Pertama – Dasar-dasar ‘aqaidiyyah (keyakinan) dari Wilayatul Faqih.
● Kedua – Pembahasan tentang Wilayatul Faqih itu sendiri, serta batas-batasnya yang luas dan sempit.
1. Dasar-Dasar ‘Aqaidiyyah Wilayatul Faqih
Sebelum masuk lebih jauh, perlu ditegaskan bahwa akal manusia atau rasio menangkap bahwa pada dasarnya tidak seorang pun memiliki otoritas atas orang lain (laa wilayata li ahad ‘alaa ahad) . Artinya, setiap manusia memiliki hak untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai kehendaknya, tanpa dapat dipaksa oleh siapa pun. Prinsip ini akan tampak sangat efektif manakala muncul keraguan ada atau tidaknya kewenangan seseorang atas diri kita—tentu diluar mereka yang telah terbukti memiliki kewenangan (wilayah) berdasarkan dalil rasional dan syar‘i.
Prinsip pertama: Wilayah Allah
Segala bentuk otoritas, terlepas luas atau sempit batasannya, harus memperoleh legitimasi dari Allah SWT, sebab Dialah pemilik sejati dari segala sesuatu—dari-Nya segala permulaan dan kepada-Nya segala kesudahan. Tidak ada sesuatu pun yang bertindak kecuali dengan kekuasaan Allah, dan tidak ada pengaruh yang terjadi kecuali melalui-Nya. Otoritas Allah atas kita memiliki arti bahwa Dialah yang menciptakan kita dan mengadakan kita dari ketiadaan. Dan tanpa itu, kita tidak akan pernah ada. Hal ini disadari oleh akal kita dan diakui oleh pemahaman kita. Otoritas ini disebut Otoritas Penciptaan (al-wilayah al-takwiniyyah), yang berarti bahwa apabila Allah menghendaki sesuatu, cukup bagi-Nya untuk berkata: “Jadilah,” maka terjadilah ia. Otoritas lainnya adalah apa yang disebut dengan Otoritas Legislasi (al-wilayah al-tashri‘iyyah), yaitu apabila Allah memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, maka wajib bagi kita menaati setiap perintah dan larangan-Nya. Sebab, Allah tidak memerintah atau melarang tanpa tujuan, melainkan dengan hikmah dan maksud tertentu. Untuk itulah Allah mengutus para nabi untuk membimbing manusia kepada-Nya dan menjelaskan hukum-hukum-Nya. Dengan demikian, akal yang mengetahui keberadaan Allah SWT, Dia pula lah yang menuntun kita kepada kewajiban untuk menaati-Nya dan menjauhi larangan-Nya.
Apa yang dikemukakan di atas telah disinggung oleh Al-Qur’an, sebagaimana dapat dilihat pada ayat-ayat berikut. Terkait Otoritas Penciptaan, Allah berfirman:
“Sesungguhnya ketetapan-Nya, jika Dia menghendaki sesuatu, Dia berkata kepadanya, ‘Jadilah!’ Maka, terjadilah (sesuatu) itu.” (QS. Yasin [36]: 82).
Sedang tentang Otoritas Legislasi, dapat dilihat pada firman-Nya:
“Ketetapan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia.” (QS. Yusuf [12]: 40).
Dari penjelasan singkat ini kita memahami bahwa pemegang otoritas utama dan tertinggi atas manusia adalah Allah SWT, pemilik otoritas sejati dan mutlak. Selain Dia tidak ada satupun yang memiliki otoritas atau kekuasaan atas manusia, kecuali jika otoritas itu diperoleh dan bersumber kepada-Nya. Jika demikian adanya maka tidak diperkenankan membantahnya dan wajib menaatinya.
Prinsip kedua:
Gerak kehidupan yang terus melaju yang disebabkan oleh pertumbuhan dan pertambahan jumlah manusia mengikuti reproduksi dari generasi ke generasi serta keragaman dan kompleksitas hubungan sosial yang muncul karenanya, telah menimbulkan penyimpangan dan pertentangan dalam masyarakat manusia. Ini tentunya tidak sejalan dengan tujuan penciptaan manusia dan kehidupan itu sendiri. Karena itu, diperlukan seorang pembimbing (mursyid) yang menuntun manusia ke jalan yang lurus dan benar. Itulah mengapa Allah, yang karena kasih sayang dan rahmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya, mengutus para nabi (as) untuk memberi petunjuk dan peringatan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur’an:
“Manusia itu umat yang satu. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 213).
Ada dua tugas utama yang diembankan Allah kepada para nabi (as): pertama, menghidupkan kembali fitrah manusia agar mereka mengenal Tuhan. Kedua, menumbuhkan dorongan spiritual dalam diri orang-orang beriman agar mereka merealisasikan kehendak Allah di bumi. Dalam hal ini sesungguhnya kehidupan para nabi terdiri dari dua fase: pertama, hanya menyampaikan risalah dan bimbingan. Ini dilakukan sebelum mereka berhasil mencapai tujuan risalahnya. Fase kedua, menjaga serta melestarikan tujuan risalah melalui otoritas legislasi yang diberikan kepada mereka, dalam arti, hak mereka untuk ditaati manusia guna mencegah penyimpangan yang dapat memundurkan kemajuan iman. Iya, para nabi (as) hanya diberi otoritas legislasi semata. Tidak otoritas penciptaan, karena otoritas penciptaan adalah hak eksklusif Sang Pencipta. Meskipun demikian, beberapa nabi diberi Allah otoritas penciptaan dalam batas tertentu, misalnya mukjizat, untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar diutus Allah untuk membimbing manusia dan bukan untuk mencari kedudukan atau kekuasaan. Sebagaimana firman Allah:
“Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah.”
(QS. Yunus [10]: 72).
Prinsip ketiga: Otoritas Imam Maksum
Fungsi kenabian (as) tidak terbatas bagi para nabi semata, karena kehidupan tidak berakhir dengan kematian para nabi, tapi terus berlanjut. Oleh karena itu diperlukan seseorang (Imam) yang melanjutkan jalan para nabi setelah mereka kembali kepada Allah Yang SWT. Fungsi itu diemban oleh seorang Imam. Dengan demikian diketahui bahwa imamah merupakan kelanjutan alami dari garis kenabian dan risalah langit, sebab manusia selalu berpotensi mengalami penyimpangan di setiap waktu dan tempat. Hal ini menuntut keberadaan para pengawas dan penjaga jalan kebenaran; dalam hal ini, sesudah para Nabi, tanggungjawab itu diemban oleh para Imam. Maka, sebagaimana para nabi, imam pun memiliki otoritas yang sama dengan Nabi agar dapat melaksanakan peran yang diembannya.
Itulah sebabnya terdapat riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa setiap nabi memiliki penerus setelahnya. Dari sinilah imamah menjadi suatu keniscayaan bagi Allah SWT, karena ia merupakan bentuk kasih sayang dan rahmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya.
Imam haruslah orang yang paling dekat dengan sang Nabi, dari sisi kemampuan dan sifat-sifatnya, sebagaimana dinyatakan dalam riwayat-riwayat, misalnya riwayat dari Imam Zain al-‘Abidin (as) bahwa:
“Tidaklah seorang Imam dari kami kecuali dia seorang yang maksum. Namun kemaksuman tidak tampak dalam bentuk lahiriah yang dapat dikenali oleh manusia; karena itu ia hanya dapat ditentukan oleh Allah.”
Artinya, penetapan Imam berada di tangan Allah SWT, bukan manusia. Sebab manusia, yang tidak mampu mengetahui batin seseorang, tidak layak menentukan siapa yang paling dekat dengan Nabi, sedangkan Allah adalah Pencipta yang Maha Mengetahui. Karena itu, menurut pandangan kami, penunjukan Imam berada di tangan Allah, sedangkan menurut sebagian kaum Muslim lain dilakukan melalui baiat dan pilihan umat.
2. Kebutuhan akan Wilayatul Faqih
Karena kondisi sosial dan politik yang sangat sulit, Imam (al-Mahdi) terpaksa gaib dan menghilang dari pandangan. Namun, kegaiban itu tidak terjadi secara mendadak, sebab hal itu berarti melempar para pengikut Ahlulbait (as) ke tangan para penguasa zalim yang nota bene dapat melenyapkan para pembela kebenaran dari kehidupan umat Islam. Untuk itu diperlukan kegaiban sementara atau yang lazim disebut dengan al-haibah al-sughra (kegaiban kecil) yang berfungsi sebagai masa persiapan yang tepat untuk membiasakan umat atas ketidakhadiran sang Imam dan sekaligus mengedukasi mereka untuk merujukkan urusan-urusan mereka kepada kepemimpinan yang sah selama masa kegaiban—yakni para duta khusus yang ditunjuk langsung oleh Imam. Masa ini berlangsung dari tahun 260 hingga 328 atau 329 H, sekitar tujuh puluh tahun, hingga konsep kegaiban mengakar kuat dan kebiasaan merujuk kepada para duta menjadi hal yang umum di kalangan pengikut.
Setelah wafatnya duta keempat, Imam tidak lagi menunjuk siapa pun sebagai pengganti, yang menandai awal dari al-ghaibah al-kubra (kegaiban besar), yang akan terus berlanjut hingga Allah mengizinkan hamba pilihan-Nya untuk muncul kembali dan memenuhi dunia dengan keadilan dan kesetaraan.
Karena itu, selama masa kegaiban, para fuqaha (ulama) memikul tanggung jawab untuk menjaga syariat, mencegah penyimpangan, dan berjuang menegakkan pemerintahan yang berlandaskan kebenaran dan keadilan Ilahi.
3. Kajian Fikih tentang Wilayatul Faqih
Dalam fikih Islam, konsep wilayah (otoritas atau kewenangan) tidak terbatas pada wilayatul faqih (otoritas faqih) saja, tetapi juga mencakup otoritas-otoritas lainnya. Misalnya:
● Otoritas seorang ayah atas anak-anaknya yang masih kecil dan anak-anaknya yang kurang waras meskipun sudah balig.
● Otoritas seorang yang mendapat amanat atau wasiat (al-washi) atas anak-anak pemberi wasiat yang masih kecil.
● Otoritas seorang ayah atas putrinya perawannya yang akil balig apabila ia hendak menikah.
● Otoritas seorang ayah atas anak-anaknya yang masih kecil.
● Otoritas pemberi utang untuk mengambil kembali uangnya dari pihak yang mengingkari atau yang menunda-nunda pembayaran, dengan catatan si penghutangt mampu membayar,
● Dan otoritas-otoritas lainnya yang disebutkan dalam kajian-kajian fikih.
Dari seluruh otoritas-otoritas itu otoritas faqih atau wilayatul faqih adalah yang paling penting, paling strategis, dan paling mencakup karena bersinggungan dengan seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat. Adapun otoritas-otoritas lainnya hanya menyangkut aspek-aspek personal dalam kehidupan umat.
Perlu ditegaskan disini bahwa seluruh ulama sepakat atas keberadaan otoritas faqih (ulama). Tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka mengenai hal ini. Perbedaan terjadi pada batas dan atau jauh mana otoritas yang dimiliki seorang. Dalam hal ini, ada tiga pandangan utama:
● Pertama, faqih memiliki otoritas mengeluarkan fatwa, memutuskan perkara, menetapkan hukum, dan menangani persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan umum (al-umur al-hisbiyyah).
● Kedua, selain otoritas di atas, faqih juga memiliki otoritas penegakan hudud (hukum pidana).
● Ketiga, sebagaimana imam maksum, faqih juga memiliki otoritas menyeluruh (al-wilayah al-ammah) yaitu dalam hal melaksanakan ketentuan-ketentuan (hukum) kecuali dalam perkara-perkara yang secara tegas dikecualikan oleh dalil, seperti jihad ofensif.
Adapun dasar penetapan otoritas faqih ini berasal dari adanya riwayat-riwayat dari para Imam Maksum (as) yang menegaskan adanya otoritas faqih, seperti riwayat: “Para ulama adalah pewaris para nabi,” atau riwayat “Segala urusan berada di tangan para ulama yang dipercaya atas hukum halal dan haram Allah.”
Selain itu juga ucapan Imam Ja‘far ash-Shadiq (as) dalam riwayat yang diterima dari ‘Umar bin Hanzhalah:
“Perhatikanlah, siapa pun di antara kalian yang meriwayatkan hadis-hadis kami, memahami hukum halal dan haram kami, serta mengetahui keputusan-keputusan kami, maka jadikanlah dia sebagai hakim (penguasa) kalian, karena aku telah menjadikannya hakim atas kalian. Jika ia telah memutuskan sesuai dengan hukum kami, tetapi keputusannya tidak diterima, maka pihak yang tidak menerima keputusannya itu sungguh telah meremehkan hukum Allah dan menolak kami. Dan barang siapa menolak kami berarti ia menolak Allah dan penolakan terhadap Allah setara dengan kemusyrikan.”
Selain dalil naqli (riwayat), terdapat pula dalil rasional bahwa siapa pun yang diwajibkan untuk menegakkan hukum Allah harus memiliki otoritas yang memungkinkannya melaksanakan hukum Allah tersebut. Ini berarti niscayanya otoritas fuqaha. Selain itu, karena para faqih adalah pihak yang paling memahami Islam melalui kemampuan mereka menggali hukum-hukum syariat, maka mereka adalah pihak yang paling layak memimpin umat, bukan di luar mereka. Karena itu, benar apa yang dikatakan: bahwa persoalan otoritas faqih adalah sesuatu yang sudah semestinya diterima secara aksiomatis dan niscaya.
Yang kita maksud dengan otoritas faqih disini ialah otoritas menyeluruh (al-wilayah al-ammah) yang dimiliki seorang faqih, yang berarti bahwa faqih mengambil peran al-Maksum dalam memimpin umat, kecuali dalam perkara-perkara yang secara khusus hanya menjadi hak al-Maksum, seperti jihad ofensif. Hal ini tidak berlaku bagi faqih pada masa kegaiban. Adapun pada bidang-bidang lainnya faqih memiliki otoritas yang sama dengan otoritas al-Maksum tanpa kurang sedikitpun. Dengan demikian, mencakup urusan harta, jiwa, dan tindakan-tindakan. Otoritas atas harta bukan berarti ia mengambil harta masyarakat, melainkan ia berhak mengatur penggunaan harta umat apabila dibutuhkan demi kemaslahatan bersama. Otoritasnya atas jiwa berarti bahwa masyarakat wajib menaati perintah dan larangannya, bukan dalam arti mereka menjadi budaknya, melainkan sebagai bentuk kepatuhan terhadap kepemimpinan syar‘i yang sah.
4. Syarat-Syarat Wilayatul Faqih
Syarat-syarat dasar bagi seorang faqih untuk memiliki wilayah adalah sebagai berikut, dan semuanya harus terpenuhi:
● Pertama, ijtihad, yakni kemampuan untuk menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil syar‘i yang valid.
● Kedua, keadilan, yakni konsistensi dalam menunaikan kewajiban dan menjauhi larangan agar pemilik otoritas tidak menyimpang dari kebenaran.
● Ketiga, kemampuan manajerial dan kepemimpinan, yaitu kemampuan mengelola urusan umat dan memanfaatkan potensi mereka secara optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Siapa pun yang tidak memenuhi syarat-syarat ini, atau setidaknya sebagian darinya, tidak berhak memegang otoritas dalam pengertian yang telah dijelaskan.
5. Ketika Ada Beberapa Faqih yang Memenuhi Syarat
Terkadang kita mendapati bahwa beberapa orang faqih secara bersamaan memenuhi syarat untuk memegang otoritas. Jika semuanya ingin menjalankan kewenangan tersebut, akan timbul pertentangan dalam keputusan yang mereka buat. Pada saat yang sama, tidak pula dapat dibenarkan membatasi otoritas hanya pada satu orang tanpa alasan yang sah, sebab hal itu dapat berujung pada tirani. Solusi yang dapat diterapkan dalam hal ini adalah memberi peran kepada umat untuk memilih salah satu dari para faqih yang memenuhi syarat tersebut. Dengan demikian, pemilihan tersebut menjadi dasar legitimasi syar‘i untuk menetapkan wilayah bagi salah satu dari mereka.
Pendekatan ini sejalan dengan teori Islam yang menempatkan kepemimpinan umat pada satu individu, sesuai dengan syarat-syarat yang telah disebutkan, disertai dengan pengawasan umat agar tidak terjadi penyimpangan.
Dari sini dapat dikatakan bahwa Wilayatul Faqih, sebagai sebuah prinsip, didasarkan pada interaksi dan keselarasan antara umat dan kepemimpinan, sehingga kepemimpinan berada di bawah pengawasan umat, dan umat wajib menaati pemimpin yang telah mereka pilih dari kalangan faqih yang layak menduduki posisi agung tersebut.
Hal ini tidak berarti meniadakan wilayah faqih-faqih lain. Wilayah mereka atas bidang-bidang lain tetap eksis, seperti wilayah dalam peradilan, pemberian fatwa, dan pengelolaan urusan publik (al-umur al-hisbiyyah), sebab fungsi-fungsi tersebut tidak bergantung pada posisi kepemimpinan umat, dan ruang lingkupnya terbatas pada individu atau entitas tertentu tanpa saling bertentangan.
6. Kepemimpinan Imam Khomeini
Pada masa Revolusi Islam yang penuh berkah—yang dengan kemenangannya atas kekuatan kekufuran dan keangkuhan global telah membuka jalan dan memberikan harapan sejati bagi seluruh umat manusia, khususnya kaum Muslimin—muncullah kepemimpinan agung Imam Khomeini (semoga Allah menjaganya), yang mengibarkan panji kebenaran, memimpin barisan, dan meraih capaian sejarah besar di tengah kegelapan abad ke-20.
Dari sudut pandang ini, menjadi kewajiban bagi seluruh Muslim untuk menaati beliau dan menerima kepemimpinannya tanpa mencari alasan untuk menghindar, serta menjadikan petunjuk dan ajarannya sebagai pedoman, karena beliau mewakili kepemimpinan Islam yang benar dan bijaksana sesuai dengan pemahaman Ilahi kita tentang masalah Wilayatul Faqih.
Demikian pula para fuqaha lain. Mereka tidak diperkenankan mengganggu kepemimpinannya. Imam Khumaini berada di garda terdepan menghadapi sistem kekufuran dan kezaliman, dan melalui sepak terjangnya mampu menggerakkan umat hingga meraih kemenangan yang nyata. Dengan demikian ia adalah figur yang paling berhak memimpin umat pada masa kini.
Dari uraian di atas kita sampai pada kesimpulan bahwa kedudukan Wilayatul Faqih merupakan posisi tertinggi dalam umat Islam selama masa kegaiban Imam Mahdi (semoga Allah mempercepat kemunculannya). Posisi ini memikul tanggung jawab untuk mengatur urusan umat dan memenuhi kepentingannya di atas jalan Ilahi yang lurus. Ia adalah proses saling menasihati dan bermusyawarah untuk memajukan peradaban umat.
Setelah Imam Khomeini (semoga Allah menyucikan rahasianya) berpulang kepada Tuhannya dengan penuh keridaan, wilayah berpindah kepada Ayatullah Agung Imam Khamenei (semoga bayangannya kekal), yang melanjutkan jalan yang telah dirintis Imam Khumaini. Dengan kepemimpinannya yang bijak, beliau telah membawa umat Islam melangkah dengan mantap menuju tujuan-tujuan besar yang kita cita-citakan sebagai kaum Muslimin yang ingin mengamalkan Islam sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, Rasul-Nya, dan para Imam Maksum (as).
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
Diterjemahkan dari tulisan al-Syaikh Muhammad Taufiq al-Miqdad dalam islam4u.com dengan judul “Wilayatul Faqih Dharurah wa Hadaf”.