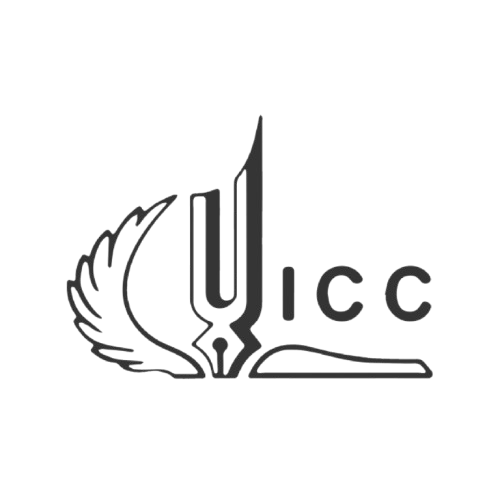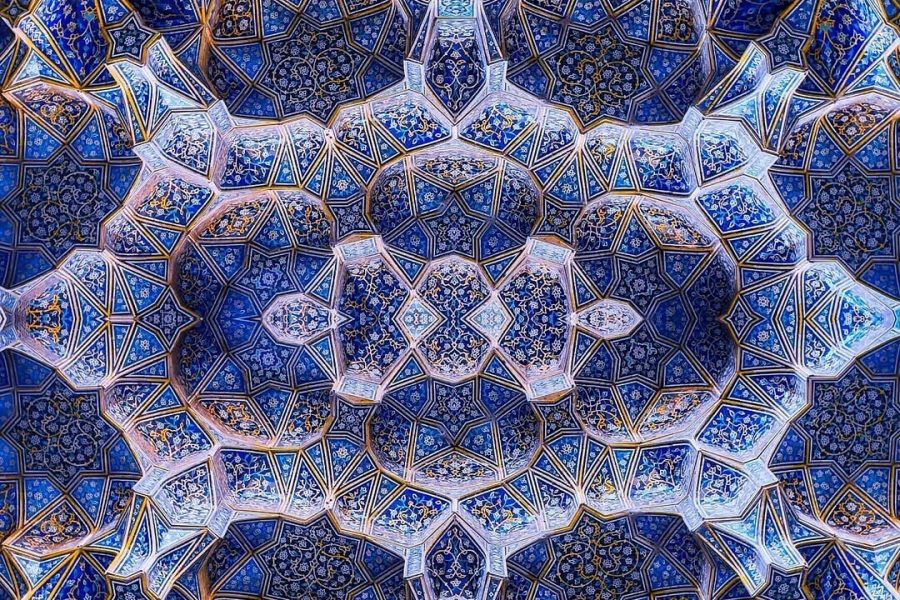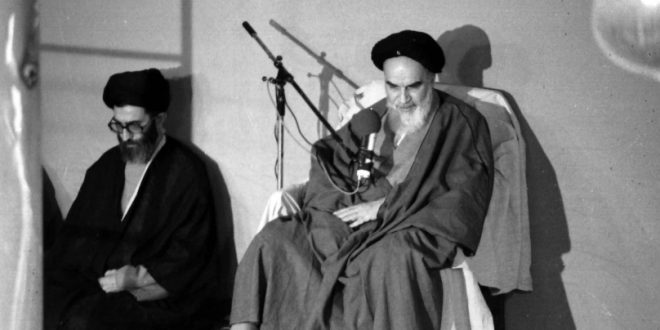Oleh: Ustaz Haidar Habballah
Pendahuluan
Pembahasan mengenai persoalan amar makruf dan nahi mungkar (menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran) memiliki banyak sisi dan dimensi. Namun, dalam tulisan ini, kami tidak akan membahas pentingnya amar makruf, ataupun kewajiban dan hukum-hukum fikihnya. Yang akan kami bahas adalah sekumpulan poin yang menurut kami sangat penting dan mendesak untuk diperhatikan, karena dapat memberikan sorotan baru terhadap isu yang sangat krusial ini.
Sebelum masuk ke inti pembahasan, saya ingin menyampaikan satu hal yang layak dicermati. Seorang orientalis Inggris bernama Michael Cook—seorang orientalis kontemporer asal Inggris yang mengkhususkan diri dalam studi-studi Islam dan merupakan profesor di Universitas Princeton—menulis sebuah buku berjudul, “Commanding Right and Forbidding Wrong in Islamic Thought” (Amar Makruf Dan Nahi Mungkar Dalam Pemikiran Islam).
Alasan dia menulis buku ini bermula dari sebuah kejadian: Suatu hari, ketika dia berada di sebuah negara Barat, dia menyaksikan sekelompok pria memperkosa seorang wanita di stasiun kereta. Wanita itu tidak bisa membela diri, dan tidak seorang pun ikut campur. Semua orang hanya berdiri di jalan tanpa peduli dan tidak merasa bertanggung jawab. Baru setelah beberapa waktu, polisi datang.
Michael Cook tertegun melihat peristiwa ini, dan sangat terkejut. Dia bertanya-tanya: Mengapa tidak ada satu pun orang yang mencegah kemungkaran seperti itu? Dia pun mulai merenungkan latar belakang budaya masyarakat ini, lalu membandingkannya dengan budaya Islam. Dia menemukan bahwa dalam Islam terdapat satu kewajiban yang sangat penting dan tidak ditemukan dalam budaya Barat.
Bahkan, menurut pandangannya, budaya Barat justru memiliki kebalikannya. Kewajiban itu adalah: amar makruf dan nahi mungkar.
Dia berkata, “Hal yang mendorong saya untuk meneliti masalah ini adalah keterkejutan saya: Mengapa peristiwa seperti itu tidak terjadi di negeri-negeri Muslim? Mengapa ketika ada kejadian semacam itu, umat Islam mengecam dan langsung bertindak untuk mencegahnya? Sedangkan di dunia Barat, secara praktis tidak ada gerakan atau reaksi spontan dari hati nurani manusia terhadap kemungkaran di hadapan mereka.”
Berdasarkan pengalaman tersebut, Michael Cook menulis buku tebalnya. Buku ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Persia, dan berbagai bahasa lainnya. Dalam bukunya, dia mengkaji amar makruf dan nahi mungkar dalam seluruh mazhab Islam, dengan merujuk pada ratusan sumber. Buku ini merupakan studi terbesar dan paling komprehensif mengenai amar makruf dan nahi mungkar—bahkan lebih luas daripada kajian-kajian yang dilakukan oleh kaum muslim sendiri—baik dari sisi penelitian, penelusuran sejarah, maupun kritik.
Michael Cook tidak membahas persoalan ini dari sudut fikih, karena ia bukan seorang ahli fikih. Namun, ia menelusuri sebuah teori penting selama kurun waktu 1400 tahun, melalui berbagai pertanyaan:
- Bagaimana teori ini berkembang?
- Bagaimana kaum Muslim memahaminya?
- Bagaimana mereka menerapkannya?
- Bagaimana kaitannya dengan kehidupan politik dan sosial?
- Bagaimana kewajiban ini membentuk rasa tanggung jawab sosial terhadap sesama?
Dengan demikian, amar makruf dan nahi mungkar bukanlah sekadar larangan terhadap satu dosa tertentu, atau sekadar perintah terhadap satu kewajiban furu’ (cabang) di sana-sini. Ini bukan persoalan kecil. Ia adalah simbol kesadaran sosial dalam Islam, dan merupakan agenda besar reformasi masyarakat, baik dari segi akhlak, sosial, pendidikan, pemikiran, maupun budaya.
Sayangnya, kita umat Islam telah mengecilkan makna besar ini dalam praktik sehari-hari. Sebagian dari kita bahkan hanya memahami amar makruf dan nahi mungkar sebatas hal-hal kecil, misalnya: ketika mendengar musik di dalam taksi, lalu menegur sopirnya dengan mengatakan, “Itu haram!”
Contoh-contoh Problematika Terkait Amar makruf dan Nahi Mungkar
Setelah penjelasan di atas, kita dapat menguraikan sejumlah problematika yang berkaitan dengan kewajiban amar makruf dan nahi mungkar ini. Kewajiban ini dahulu oleh sebagian tokoh kelompok Ikhwanul Muslimin disebut sebagai “kewajiban yang terlupakan” (al-fariḍah al-gha’ibah). Jika digabungkan dengan jihad, maka keduanya dikenal sebagai dua kewajiban yang hilang.
Istilah ini disebut dalam sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Insinyur Muhammad Abdussalam Faraj, berjudul, “al-Fariḍhah al-Ghaibah” (Kewajiban Yang Terlupakan). Buku ini merupakan salah satu pondasi pemikiran awal Ikhwanul Muslimin. Penulisnya dieksekusi mati pada tahun 1982 terkait kasus pembunuhan Presiden Mesir kala itu, Anwar Sadat.
Problematika Pertama: Minimnya Teori dan Ijtihad Mendalam
Jika kita menelusuri sedikit saja karya-karya para ulama, pemikir, dan fukaha, kita akan menemukan bahwa kajian tentang kewajiban ini sangat terbatas dan sedikit. Tidak ada perhatian yang layak terhadap masalah ini, baik dalam studi fikih maupun teologi (kalam) saat ini.
Pada masa-masa tertentu, kewajiban ini merupakan slogan utama umat Islam, terutama di kalangan kaum Muktazilah dan Zaidiyah. Kaum Muktazilah bahkan menganggap amar makruf dan nahi mungkar sebagai salah satu dari lima pokok agama (uṣuludin), bukan sekadar cabang. Mereka berpendapat bahwa dalil kewajiban ini bersumber dari akal, bukan dari nash (dalil tekstual), sedangkan nash hanya bersifat pendukung. (Lihat: Syaraḥ al-Uṣhul al-Khamsah, hal.89 dan 501)
Karena itu, mereka memahami amar makruf sebagai mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk politik, dan bahkan memasukkan konsep revolusi terhadap kezaliman ke dalam makna nahi mungkar.
Hal ini dapat terlihat secara nyata dalam persoalan fikih, seperti: bagaimana hukum orang yang meninggalkan amar makruf dan nahi mungkar? Kaum Muktazilah dan Zaidiyah sangat keras dalam persoalan ini, karena mereka meyakini bahwa imam yang benar adalah imam yang menegakkan amar makruf dan nahi mungkar. Setiap imam yang berdiam diri dan tidak melakukan dua hal ini bukanlah imam sejati. Dalam pandangan mereka, imamah adalah tugas, bukan kehormatan.
Jika kita membaca sejarah secara objektif, kita akan melihat bahwa kaum Muktazilah dan Zaidiyah memiliki peran besar dalam menegakkan amar makruf dan nahi mungkar. Namun, secara umum, tidak ada perhatian serius secara ilmiah dan ijtihadi terhadap kewajiban ini selama sekitar tujuh abad terakhir.
Jika kita bandingkan antara hasil-hasil fikih tentang amar makruf dan nahi mungkar dengan topik-topik fikih lainnya—seperti Bab Thaharah (Bersuci) dan sejenisnya—kita akan menemukan jurang perbedaan yang besar. Hampir tidak ada penambahan signifikan dalam kajian amar makruf dibandingkan dengan perkembangan luar biasa dalam topik-topik fikih lainnya.
Sebagai contoh: Jika kita melihat bahasan tentang jual beli atau transaksi bisnis (muamalah) dalam fikih Islam, kita akan menemukan bahwa selama empat abad terakhir, terjadi loncatan luar biasa, terutama dalam fikih Syiah Imamiyah. Jika kita baca kitab fikih muamalah empat abad lalu dan membandingkannya dengan yang sekarang, kita akan melihat perkembangan yang sangat signifikan.
Namun, jika kita membaca buku tentang amar makruf dan nahi mungkar yang ditulis lima abad lalu, dan membandingkannya dengan buku terkini, kita nyaris tidak akan menemukan perbedaan berarti. Artinya, tidak terjadi kemajuan atau perhatian yang mendalam terhadap topik ini sebagaimana mestinya.
Dan barangkali lompatan terpenting—dalam pandangan pribadi saya—yang disaksikan oleh fikih Syiah Imamiyah mengenai topik ini adalah kitab (الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر – Perintah kepada Kebaikan dan Pencegahan dari Kemungkaran) dari Tahrir al-Wasiilah, karya Imam Khomeini. Jika kita menelusuri fikih Amar Makruf dan Nahi Mungkar dari zaman Syekh Kulaini (w.329 H) hingga zaman Imam Khomeini, dan kita mengikuti kitab-kitab permohonan fatwa dan fatwa-fatwa fikih, kita akan menemukan bahwa dengan kitab Tahrir al-Wasiilah kita menyaksikan lompatan baru yang berbeda, di mana Imam Khomeini memperluas ide tersebut untuk mencakup kehidupan sosial, politik, dan hubungan dengan otoritas.
Sebagai bentuk keadilan, ada lompatan-lompatan lain, tetapi sedikit dan terbatas, dan tidak dalam bentuk yang kita saksikan pada bab-bab fikih lainnya, terutama bab-bab thaharah (bersuci), ibadah, makasib (pekerjaan/usaha), dan jual-beli.
Karena itu, pengembangan harus dilakukan, dari beberapa sisi yang dituntut oleh masa yang kita jalani, untuk topik Amar Makruf dan Nahi Mungkar: dari sisi ijtihad, ilmiah, Alquran, fikih, tafsir, dan hadis.
Permasalahan Kedua: Krisis Sarana dan Alat
Semua ini berada di sisi penelitian ilmiah dalam masalah ini. Adapun pada lini sarana dan alat, ada permasalahan lain yang kita hadapi, yaitu metode, cara, sarana, dan mekanisme yang digunakan dalam Amar Makruf dan Nahi Mungkar.
Syekh Murtadha Muthahhari berkata sekitar empat puluh tahun lalu, “Saat ini seharusnya Amar Makruf dan Nahi Mungkar ditutup dan kewajiban ini dibatalkan; karena orang-orang yang menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran di zaman kita justru menjauhkan orang dari agama dengan cara dan metode mereka.” (Lihat: Ru’aa Jadidah fi al-Fikr al-Islami, jilid 3, halaman 94-95). Jadi, ada kebutuhan—dari sudut pandang Muthahhari—untuk berinovasi dan mengembangkan metode; karena sebagian dari kita masih menggunakan cara-cara lama. Contohnya: Ada gagasan bahwa amar makruf harus dalam bentuk perintah, misalnya, “Salatlah!”. Inilah amar makruf. Adapun jika kita berkata kepadanya, “Salat itu baik, dan sebaiknya kamu shalat,” ini adalah nasihat, bukanlah amar makruf! Seolah-olah ide amar makruf berpusat pada unsur langsung berupa perintah atau larangan. Sementara itu, unsur-unsur tidak langsung luput dari kesadaran kita; karena dulu cara-cara itulah yang digunakan orang; sebab tidak ada media massa, sekolah, sarana pendidikan, atau informasi. Dan sebagian dari kita masih menggunakan cara-cara lama yang sama dalam amar makruf. Masalahnya bukan pada penggunaan yang lama, tetapi mari kita pikirkan juga cara-cara yang baru.
Syekh Muthahhari merasakan bahwa metode kita kasar/kurang halus, dan karena itu dia sampai pada tahap menuntut penutupan amar makruf. Muthahhari tidak bermaksud agar kita menutup kewajiban amar makruf, melainkan dia bermaksud mengeluhkan metode kita yang kasar, yang telah menjauhkan orang dari agama.
Sebagian ulama berkata, “Ketika kamu ingin menangkap ikan, kamu harus meletakkan makanan yang cocok untuknya dan yang ia nikmati, bukan makanan yang cocok untukmu.” Kita harus mengubah metode sesuai dengan keyakinan dan budaya orang.
Hari ini, media berperan bahkan dalam selera kita terhadap keindahan. Kita lalai dari pemandangan ini, kita masih berbicara secara langsung dengan pihak lain.
Karena itu, ada kebutuhan besar untuk pengembangan, terutama karena ada fenomena di Barat yang disebut “Ateisme Baru”. Ateisme ini tidak hanya berbicara tentang keberadaan Tuhan. Itu tidak hanya didasarkan pada penolakan atau tidak penolakan terhadap dasar-dasar metafisika, melainkan Ateisme Baru, yang menyaksikan lonjakan besar setelah sebelas September, didasarkan pada ide sentral, yaitu, “Agama merugikan manusia.” Buktinya, “Lihatlah apa yang telah dilakukan agama terhadap umat Islam! Dan lihatlah kekejaman dan kekerasan yang ditimbulkan agama kepada kita di berbagai belahan dunia.” Inilah yang ingin mereka fokuskan, memanfaatkan kegagalan kita, dan kegagalan banyak bangsa yang religius, dan mereka memanfaatkan insiden sebelas September dan lainnya, untuk mengatakan, “Apa yang dihasilkan Islam—bahkan setiap agama—adalah kekerasan, kekejaman, kekasaran, pembunuhan, kehancuran, perpecahan. Agama tidak mengandung cinta atau komunikasi, melainkan keterputusan dan kebencian.” Hasilnya adalah agama berubah menjadi momok dari sudut pandang mereka.
Dari sini, kita harus mengembangkan metode kita untuk menghapus citra yang ingin dilekatkan pada agama ini, tanpa mengubah sedikit pun hukum syariat, dan tanpa mundur dari keyakinan, konsep, ide, dan prinsip kita. Pembicaraannya adalah tentang metode, cara, sarana, dan mekanisme, meskipun saya percaya bahwa banyak konsep, pandangan, fikih, dan visi kita juga memiliki peran mendalam dalam situasi kita saat ini, dan bahwa masalahnya tidak berhenti pada batas-batas metode, tetapi melampauinya, namun masalah metode juga sangat penting.
Selama abad terakhir, ada aktivitas seputar kewajiban ini dari tiga sisi:
Sisi Pertama: Sekelompok ulama, pemikir, cendekiawan, dan ahli fikih bangkit untuk menyatakan perlunya menghidupkan kembali kewajiban ini; karena ia adalah kewajiban yang mati dan tertidur, tidak ada yang mempraktikkan amar makruf, bahkan bukan bagian dari literatur kita.
Sisi Kedua: Pengembangan metode juga. Banyak yang telah ditulis tentang topik ini, tetapi saya percaya bahwa apa yang telah ditulis berbeda dari apa yang dibutuhkan oleh masa kita ini (masa globalisasi) atau setelah runtuhnya Blok Sosialis; di mana dunia telah berubah, aturan main telah berubah, dan kita harus mengubah posisi dan penempatan diri kita, sesuai dengan perubahan aturan main di dunia.
Sisi Ketiga: Memanfaatkan ide amar makruf dan nahi mungkar dalam kerangka konsep Kebangkitan Islam; karena kita—sejak pertengahan abad kesembilan belas hingga hari ini—menyaksikan sekelompok ulama besar yang menggagas teori Kebangkitan Islam, yang mengatakan: bahwa topik amar makruf adalah salah satu sarana besar dan mendasar yang memungkinkan kita untuk mencapai Kebangkitan Islam yang dicita-citakan.
Maka, kita membutuhkan:
- Ijtihad fikih yang diperluas dalam topik ini, masing-masing dari posisinya.
- Kita membutuhkan konferensi dan seminar tentang pengembangan sarana amar makruf dan nahi mungkar, dengan meminta bantuan dari para ahli di berbagai bidang, terutama bidang ilmu humaniora dalam masalah pendidikan, pengajaran, media, manajemen, pengaruh psikologis, dan lain-lain.
- Kita membutuhkan seminar (walaupun tertutup) untuk peninjauan dan kritik diri, yang terus berlanjut; untuk melihat di mana titik-titik kelemahan kita? Mengapa kita gagal di tempat tertentu? Bagaimana cara mengembangkan unsur-unsur kekuatan dan mengatasi unsur-unsur kelemahan?
- Kita harus melakukan aktivitas untuk menghadirkan konsep Alquran ini, menyerukannya, mempromosikannya, dan menyebarkan istilah ini dalam kehidupan masyarakat; karena agak luput dari perhatian.
Permasalahan Ketiga: Pembatasan Kewajiban Amar Makruf dan Nahi Mungkar
Banyak orang beranggapan—bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam fikih dan fatwa—bahwa kewajiban ini adalah tugas para ahli fikih, syekh, dan ulama, karena mereka mengetahui halal dan haram, sedangkan masyarakat umum seolah-olah tidak ada urusan dengan hal itu, dan seandainya pun mereka berkepentingan dengan kewajiban ini, itu hanya dalam bentuk individu yang sangat terbatas, yang tidak menjadi bagian dari program hidup mereka.
Konsep ini sepenuhnya salah menurut pendapat mayoritas ulama Muslim, kecuali segelintir kecil dari mereka di masa lalu; karena kewajiban amar makruf dan nahi mungkar tidak ada bedanya antara ulama agama dan non-ulama, dan tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan; ini adalah kewajiban umum. Nas-nas Alquran dan hadis jelas menunjukkan tidak adanya diskriminasi dalam kewajiban ini, bahkan jika kita merenungkan sedikit nas-nas kitab dan sunah, kita akan menemukan bahwa kewajiban ini memiliki tiga sisi:
- Sisi Individu: Seseorang memerintahkan sesama manusia.
- Sisi Otoritas/Pemerintahan: (QS. al-S. al-Hajj:41). Negara atau otoritas dalam Islam memiliki tanggung jawab amar makruf dan nahi mungkar, dan tidak boleh mengambil sikap netral dalam hal itu; karena pemberdayaan di muka bumi berarti otoritas, baik kesukuan, agama, media, politik, ekonomi, atau lainnya. Dan Negara adalah bentuk pemberdayaan yang paling menonjol, dan setiap orang yang diberdayakan Allah di muka bumi, baik individu maupun kelompok, dituntut untuk melaksanakan tugas amar makruf dan nahi mungkar, dan memperbaiki urusan masyarakat dan lingkungannya.
- Sisi Kemasyarakatan (Komunitas): Artinya, amar makruf dan nahi mungkar adalah fungsi kemasyarakatan. Seluruh masyarakat berkepentingan dengan masalah ini, baik ada otoritas maupun tidak.
Ada pendapat Syekh Muhammad Mahdi Syamsuddin yang menyatakan bahwa beban syariat (taklif) dalam Islam terbagi menjadi dua: Beban Individual (Takalif Fardiyyah), di mana khitab (seruan) Alquran dan sunah ditujukan kepada individu; dan Beban Kemasyarakatan (Takalif Mujtama’iyyah), di mana khitabnya ditujukan kepada Umat (Syamsuddin, Jihadul Ummah: 47-59).
Banyak hal yang oleh para ahli fikih disebut Kewajiban Kolektif (Wajibat Kifa’iyyah), oleh Allamah Syamsuddin disebut sebagai Kewajiban Kemasyarakatan, atau Kewajiban Umat. Contohnya adalah kewajiban jihad. Kewajiban ini tidak ditujukan hanya kepada saya sendiri; karena tidak ada artinya bagi saya untuk berjihad sendirian; karena sifat jihad adalah sifat kolektif (tentu saja yang saya maksud adalah jihad militer/perang). Seruan ini ditujukan kepada kelompok, dan kelompok itulah yang dituntut untuk berjihad, terlepas dari setiap individu secara terpisah. Sejalan dengan jihad, terdapat amar makruf dan nahi mungkar, yang merupakan salah satu fungsi yang diperintahkan kepada Umat sebagai Umat, “Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia…” (QS Ali Imran:110), dan Allah tidak mengatakan, “Kamu, wahai muslim, adalah individu terbaik yang dilahirkan untuk manusia.”
Jadi, kewajiban ini berbeda dengan kewajiban melaksanakan salat di tengah malam; karena melaksanakan salat adalah urusan individu yang dilakukan oleh mukallaf (orang yang dibebani kewajiban) sendirian, meskipun memiliki dampak sosial lainnya. Adapun kewajiban amar makruf terkadang dilihat sebagai kewajiban individu; di lain waktu sebagai kewajiban keluarga, “Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan bersabarlah dalam mengerjakannya…” (QS Thaha:132); terkadang dilihat sebagai fungsi otoritas/pemerintahan, “Orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi…” (QS. al-S. al-Hajj:41); dan yang keempat dilihat sebagai kewajiban kolektif, di mana harus ada kelompok dalam umat yang dimobilisasi—sebagai sebuah kelompok—untuk memerintah dan mencegah, “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat…” (QS. Ali Imran:104); dan yang kelima dilihat sebagai kewajiban seluruh Umat, “Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran…” (QS Ali Imran:110).
Karena itu, kewajiban ini memiliki berbagai sisi, dari individu, hingga keluarga, hingga otoritas/pemerintahan, hingga pembentukan kelompok-kelompok di dalam Umat yang fungsi utamanya adalah pekerjaan ini, hingga menjadi fungsi Umat secara keseluruhan—yaitu, seluruh Umat Islam memiliki misi terhadap dirinya sendiri, dan terhadap umat-umat lain, yang harus mereka lakukan. Jadi, ini adalah tugas semua orang, masing-masing sesuai dengan kemampuannya, dan sesuai dengan tempatnya di dunia ini. Bahkan masalahnya mungkin melampaui ini di zaman kita—seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama—di mana sebagian Kewajiban Kolektif (Kifa’iyyah) kadang-kadang berubah menjadi Kewajiban Individual (‘Ainiyyah). Sama seperti kondisi seseorang di gurun yang bepergian bersama temannya, lalu temannya meninggal, dia harus mengurus jenazahnya mulai dari mengubur, mengkafani, dan menyalatinya, padahal semua ini adalah kewajiban kolektif, tetapi karena tidak ada orang lain selain dia, kewajiban ini berubah dari kewajiban kolektif menjadi kewajiban individual. Setiap kali tidak ada yang bertindak dalam jumlah yang memadai, kondisi menjadi lebih mendekati individual.
Di era kita ini, sebagian ulama berpendapat bahwa kewajiban ini telah berubah dari status kolektif menjadi status individual; karena sedikitnya jumlah orang yang cakap untuk bertindak dibandingkan dengan besarnya tantangan, dalam arti bahwa jika Anda membandingkan jumlah orang yang bertindak—meskipun banyak—dalam masalah amar makruf dengan besarnya tantangan, invasi budaya, dan tingkat penyimpangan moral yang ada di masyarakat, Anda akan menemukan bahwa mereka tidak mampu mencakup area ini. Oleh karena itu, orang lain juga dituntut untuk bertindak; karena rasio tindakan terhadap tantangan tidak seimbang, dan yang dituntut adalah adanya kesetaraan, minimal dalam batas terendah.
Baiklah untuk kita tunjukkan di sini bahwa surah al-Ashr menyajikan prinsip yang sangat penting, yaitu, “…dan saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran” (QS. al-S. al-Ashr:3), yaitu saling menasihati (tawashi-engkau menasihatiku, dan aku menasihatimu), dari al-muwaasaah (mufa’alah-interaksi timbal balik) antara dua pihak. Ini juga merupakan salah satu prinsip amar makruf, dan menghasilkan konsep kemasyarakatan untuk, “Jagalah dirimu…” (QS. al-S. al-Maidah:105), alih-alih konsep individual yang khusus, seperti yang akan kita tunjukkan. Ini adalah prinsip yang membuka pintu bagi para ulama untuk mencegah kemungkaran dari masyarakat dan bagi masyarakat untuk mencegah kemungkaran dari para ulama jika salah satu pihak melakukannya, tanpa membatasi pencegahan dan nasihat hanya pada satu pihak saja.
Hal penting dalam hal ini adalah bahwa ketika amar makruf dan nahi mungkar tidak dikhususkan untuk ulama agama, itu berarti setiap individu muslim memiliki hak, bahkan kewajiban, untuk memainkan peran ini, tidak hanya terhadap satu sama lain, tetapi juga terhadap ulama agama itu sendiri. Tidak ada satu pun teks dalam Alquran atau Sunnah yang sahih yang menghentikan kewajiban ini jika ingin diterapkan pada para pemuka agama itu sendiri. Oleh karena itu, masyarakat umum, jika mereka melihat kemungkaran yang dilakukan oleh seorang ulama agama, harus mencegahnya dari kemungkaran itu. Statusnya sebagai bagian dari kalangan ulama agama tidak memberinya kekebalan apa pun untuk dibimbing atau dicegah oleh masyarakat, sesuai dengan kaidah syariat yang juga harus terpenuhi di sini. Dengan demikian, apa yang diajukan oleh sebagian orang, bahwa para pemuka agama, ahli fikih, dan marja’ mereka berada di atas pelaksanaan kewajiban bimbingan, pencegahan kemungkaran, atau amar makruf terhadap mereka, tidak memiliki dasar kecuali beberapa pertimbangan sosial, seperti: menjaga kedudukan mereka, bahwa nilai agama ada pada mereka, dan bahwa mengkritik, mencegah, atau membimbing mereka tentang suatu hal di sana-sini adalah merendahkan atau melemahkan agama… Justru sebaliknya, para ulama agama harus mendidik Umat untuk menasihati mereka, mencegah mereka, dan meluruskan mereka jika mereka melakukan sesuatu yang tidak pantas.
Permasalahan Keempat: Amar Makruf dan Budaya Ketidakpedulian
Di sisi lain dari semua ini, terkadang kita dihadapkan pada masalah yang mendasari logika yang mirip dengan logika yang dikritik oleh (Michael Cook), yaitu gagasan (Ketidakpedulian), yang mungkin sebagian orang sandarkan pada firman Allah Ta’ala, “Wahai orang-orang yang beriman! Jagalah dirimu! Orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk…” (QS. al-S. al-Maidah:105). Ayat ini diperdebatkan di kalangan ulama: Apakah dia bertujuan untuk mendirikan prinsip ketidakpedulian terhadap orang lain atau tidak? Ayat itu jelas, “Jagalah dirimu…” Artinya, Anda tidak berkepentingan kecuali dengan diri Anda sendiri, dan mendahulukan, “Jagalah dirimu…” untuk menunjukkan pembatasan (hashr), sesuai dengan kaidah bahasa Arab, yang berarti: tidak ada kewajiban atas Anda kecuali diri ini. Jadi, gagasan ketidakpedulian ada, baik dengan pembenaran agama—berdasarkan ayat ini—maupun dengan pembenaran lain, dan ini mengokohkan prinsip yang mengatakan: Saya tidak berkepentingan, atau intervensi dalam kehidupan orang lain adalah ide yang salah, dan saya tidak boleh ikut campur dalam urusan mereka.
Beberapa riwayat sejarah menunjukkan bahwa gagasan mengandalkan ayat Alquran ini untuk membangun logika ketidakpedulian terhadap masalah Umat dan masalah penyimpangan berasal dari sekelompok muslim yang menyatakan logika ini, mengandalkan ayat ini setelah wafatnya Rasul yang Mulia. Mungkin orang yang mengatakan ini menyaksikan perpecahan dalam umat, lalu dia berkata: Saya tidak ada hubungannya. Kelompok ini tidak diketahui namanya, tetapi disebutkan dalam riwayat sejarah yang dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal (Musnad Ibn Hanbal, jilid 1, halaman 5).
Pertanyaannya di sini adalah: Bagaimana kita memahami logika ketidakpedulian dalam ayat tersebut? Dan bagaimana kita menghadapi logika ini yang ada di kalangan kita hari ini?
Ada beberapa jawaban dan upaya yang beragam untuk menguraikan makna ayat mulia ini. Sebagian di antaranya tidak kami setujui, meskipun ini bukan tempat untuk diskusi terperinci. Yang terpenting adalah:
Jawaban Pertama: Apa yang disebutkan oleh sebagian ulama, yang mengatakan bahwa ayat ini jelas bertentangan dengan prinsip Amar Makruf, dan karena kontradiksi ini tidak dapat dipecahkan, mereka mengatakan: Ayat ini dinasakh (dibatalkan) oleh ayat-ayat jihad dan perang serta ayat-ayat selanjutnya (Muhammad Hasan an-Najafi, Jawahir al-Kalam 30: 34).
Namun, masalahnya adalah ayat ini termasuk ayat-ayat Surah Al-Ma’idah, yang merupakan salah satu yang terakhir diturunkan dari Alquran al-Karim, yang menuntut anggapan bahwa ayat ini Makkiyah, tetapi ditempatkan dalam Surah Madaniyah, dan hal seperti ini ada contohnya dalam ilmu-ilmu Alquran dan kitab-kitab tafsir.
Jawaban Kedua: Apa yang disebutkan oleh sebagian ulama (Al-Fakhr ar-Razi, Tafsir al-Kabiir 12: 112), bahwa memungkinkan untuk menyelaraskan atau mendamaikan antara ayat ini dengan ayat-ayat Amar Makruf dan Nahi Mungkar lainnya; yaitu bahwa ayat ini ingin mengatakan: Wahai orang-orang yang beriman, kesesatan dan penyimpangan orang lain tidak akan merugikan Anda sedikit pun, baik di dunia maupun di akhirat, artinya penyimpangan salah satu kerabat, tetangga, atau masyarakat umum tidak merugikan Anda sedikit pun:
(…dan seseorang tidak akan memikul dosa orang lain…) (QS Al-An’am: 164).
Namun, upaya jawaban ini dapat menjelaskan kepada kita firman Allah Ta’ala:
(Orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk…) (QS Al-Ma’idah: 105), tetapi tidak menjelaskan firman-Nya:
(Jagalah dirimu…). Karena kalimat ini mengandung kata kerja perintah, maka ia berarti: Engkau hanya berkepentingan dengan dirimu sendiri.
Jawaban Ketiga: Apa yang disampaikan oleh sebagian ulama juga, bahwa (laam – huruf L) dalam ayat Alquran ini adalah laam an-nahyi (lam larangan), sehingga ayat tersebut berarti: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah agama, ketakwaan, keadilan, dan keimanan kalian, dan jangan biarkan orang lain merusak agama dan keimanan kalian setelah kalian mendapat petunjuk. Hal ini tidak bertentangan dengan prinsip Amar Makruf dan Nahi Mungkar. Oleh karena itu, saya wajib menjaga diri, memperhatikannya, dan tidak membiarkan orang lain merusak diri saya secara moral, spiritual, dan perilaku, dan pada saat yang sama saya wajib memperbaiki mereka, sehingga tidak ada kontradiksi di antara keduanya.
Jawaban Keempat: Apa yang dikemukakan oleh Syekh Muntaziri, bahwa ayat ini dipahami secara keliru. Semua yang ingin dikatakan ayat ini adalah: Wahai orang-orang yang beriman, kalian bertanggung jawab atas diri kalian sendiri. Kalian, pada Hari Kiamat, akan datang dengan menanggung dosa-dosa yang telah kalian lakukan sendiri.
(Tidak akan merugikanmu…), artinya jika orang lain menyimpang, kalian tidak menanggung tanggung jawab dan beban dosa perbuatan mereka pada Hari Kiamat (Husain Ali al-Muntaziri, Dirasat fi Wilayat al-Faqih 2: 240). Setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri, dan apa yang dilakukan oleh dirinya sendirilah yang akan ia tanggung dosanya pada Hari Kiamat. Adapun apa yang dilakukan orang lain, itu bukan tanggungan Anda.
Kami serahkan pembahasan terperinci mengenai makna ayat mulia ini kepada apa yang telah kami bahas dalam buku kami (Fiqh al-Amr bil Ma’ruf wan Nahy ‘anil Munkar: 86-98), silakan merujuknya.
Permasalahan Kelima: Amar Makruf dan Krisis Ketegangan Psikologis pada Para Da’i dan Penyampai Pesan
Ayat yang memunculkan gagasan ketidakpedulian ini pada hakikatnya menyerupai sekelompok ayat yang mendirikan prinsip penting dalam Amar Makruf, yaitu agar kita tidak menyusahkan diri sendiri dan saraf kita. Ada sebagian orang di kalangan kita yang beragama, ketika mereka melihat penyimpangan dalam bentuk apa pun, mereka berusaha mengubahnya, dan orang lain tidak merespons mereka, sehingga mereka menjadi seolah-olah bertanggung jawab atas orang lain, lalu mereka emosi, membakar saraf mereka, dan mengalami tekanan psikologis yang parah. Allah telah mengingatkan Rasul-Nya tentang masalah ini beberapa kali dalam Alquran:
Allah Ta’ala berfirman:
(Maka barangkali engkau akan membinasakan dirimu karena bersedih hati mengikuti jejak mereka, setelah mereka tidak beriman kepada keterangan ini) (QS Al-Kahf: 6).
Artinya, barangkali engkau membinasakan dirimu atas mereka karena mereka tidak beriman. Hidayah ada di tangan Allah, bukan di tangan kita, dan tugasmu adalah mendakwahi mereka.
Dan Dia berfirman:
(Boleh jadi engkau akan membinasakan dirimu karena mereka tidak menjadi orang-orang yang beriman) (QS Asy-Syu’ara: 3).
Manusia secara alami biasanya menanti-nanti hasil perbuatan, sehingga ia menjadi tegang dan terburu-buru. Oleh karena itu, ayat berikutnya menjawabnya bahwa jika Allah ingin marah seperti Anda, atau menjadi emosi, atau binasa diri-Nya, Dia akan menurunkan ayat dari langit, dan menyelesaikan masalah:
(Jika Kami kehendaki, niscaya Kami turunkan kepada mereka suatu tanda dari langit, sehingga leher-leher mereka tunduk kepadanya) (QS Asy-Syu’ara: 4).
Maka, ini adalah prinsip penting yang dapat kita sebut: (Prinsip Moderasi dalam Memikul Beban Keagamaan), agar kita tidak terlihat tegang seolah-olah kita kehilangan kendali diri. Allah Ta’ala berfirman:
(…dan aku bukanlah penanggung jawab atas urusanmu) (QS Yunus: 108).
Maksudnya, saya bukanlah wakil (penanggung jawab) atas urusan kalian, tetapi Tuhan kalianlah yang bertanggung jawab.
Kita menyeru orang lain, jika mereka merespons, alhamdulillah, dan jika tidak, urusan kembali kepada mereka. Inilah logika tawakal kepada Allah; karena kendali urusan ada di tangan-Nya subhanahu wa ta’ala, dan alam roh dan jiwa berada di bawah kekuasaan-Nya. Ketegangan, emosi, dan kehilangan kendali diri bukanlah strategi kita. Sebaliknya, kita menyusun rencana dan program, mengetahui bahwa perkara hati ada di tangan Allah tabaraka wa ta’ala, bukan di tangan kita. Yang penting adalah kita menjalankan tugas kita, barang siapa mendapat petunjuk, itu untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak mendapat petunjuk, urusannya kembali kepada Allah subhanahu, dan kita mendoakannya agar mendapat hidayah dan taufik.
Kesimpulannya: Amar Makruf dan Nahi Mungkar adalah fungsi sosial, politik, individual, keluarga, dan keumatan, yang dituntut dari semua orang. Kita tidak berhak untuk mengangkat tanggung jawab ini dan meletakkannya hanya di pundak para ulama; karena setiap dari kita dituntut, bahkan tidak jauh kemungkinannya bahwa tanggung jawab ini telah memasuki wilayah kewajiban individual (Wajib ‘Aini), dan tidak ada gagasan ketidakpedulian umum dalam budaya agama, melainkan tanggung jawab besar berada di pundak semua orang, tanpa membuat mereka berada dalam kondisi ketegangan dan tekanan psikologis yang tidak beralasan.
Permasalahan Keenam: Pelumpuhan Kewajiban Karena Hilangnya Pengaruh
Para ahli fikih menyebutkan syarat-syarat untuk Amar Makruf dan Nahi Mungkar. Di antara syarat-syarat tersebut adalah syarat adanya kemungkinan pengaruh. Jika tidak ada kemungkinan pengaruh pada pihak lawan, maka tidak wajib untuk memerintah dan melarangnya. Gagasan ini benar, tetapi dalam praktiknya dipahami atau diterapkan dengan cara yang membingungkan.
Para ahli fikih—seperti yang ditunjukkan oleh Sayyid Khomeini (Tahriir al-Wasiilah 1: 469)—mengatakan bahwa kemungkinan pengaruh memiliki berbagai sisi. Misalnya: Zaid minum khamr (minuman keras), lalu saya katakan kepadanya, “Ini haram,” dan saya tahu bahwa perkataan saya kepadanya tidak mempengaruhinya. Di sini kita katakan: tidak ada kemungkinan pengaruh, dan hasilnya adalah tidak ada kewajiban yang mengikat bagi saya terhadapnya setelah itu dalam masalah ini selama keadaannya tetap demikian.
Ini adalah pandangan individual yang oleh Sayyid as-Sadr disebut (Kecenderungan Kontraksi dalam Fikih). Ada orang yang berpikir bahwa hukum-hukum diatur dengan cara ini secara praktis, padahal kita harus berpikir, saat kita berurusan dengan kewajiban perintah dan larangan, sebagai kelompok besar yang tersebar di Umat, di mana setiap individu dari kelompok ini memerintah dan melarang satu atau dua orang. Di sini, saya harus melihat keadaan saya sebagai kelompok. Apakah tindakan semua individu dalam kelompok dapat menimbulkan pengaruh pada tingkat individu atau sosial, meskipun individu ini atau itu, dalam keadaan tertentu, tidak menemukan kemungkinan pengaruh pada individu ini atau yang lain?
Adanya keadaan Amar Makruf dalam masyarakat, bahkan dengan hilangnya pengaruh parsial di sana-sini, dengan sendirinya memiliki pengaruh pada orang-orang, artinya orang yang melakukan kemungkaran tidak merasakan ketenangan batin. Ini juga merupakan salah satu bentuk pengaruh. Gagasan pengaruh tidak bersandar—menurut saya—pada teks agama yang pasti sanad dan maknanya, melainkan bertumpu pada pendekatan rasional terhadap sifat kewajiban dan konteksnya (Lihat: Haidar Hubballah, Fiqh al-Amr bil Ma’ruf wan Nahy ‘anil Munkar: 339-348). Diamnya orang-orang yang menyeru kepada kebaikan membuat sebagian besar orang tidak merasa bahwa apa yang mereka lakukan adalah dosa. Inilah makna riwayat yang mengatakan, “Bagaimana dengan kalian jika kebaikan menjadi kemungkaran dan kemungkaran menjadi kebaikan?” (Tafshil Wasail asy-Syi’ah 16: 122). Ketika orang-orang yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran diam, dan penyimpangan moral dan sosial menyebar di Umat, orang-orang tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah kemungkaran.
Maka, adanya fenomena Amar Makruf secara kolektif mengarah pada perasaan para pelaku dosa bahwa setidaknya ada sudut pandang yang mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan adalah tidak benar.
Saya akan berhenti sebentar pada sebuah kisah yang disebutkan dalam Alquran, yang mendapat perhatian sebagian mufasir dalam topik Amar Makruf, yaitu Kisah (Ash-hab as-Sabt – Penduduk Hari Sabat). Dahulu ada sekelompok Bani Israil yang tinggal di tepi laut, dan mereka adalah orang-orang fasik. Allah—karena kefasikan mereka—ingin menguji mereka, Dia berfirman:
(Maka karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan bagi mereka…) (QS An-Nisa: 160).
Huruf (ba’) dalam ayat tersebut adalah sebabiah (menunjukkan sebab), artinya: karena kezaliman mereka, makanan yang baik-baik diharamkan bagi mereka. Allah ingin menghukum mereka, maka Dia mengharamkan mereka menangkap ikan pada hari Sabt (Sabtu). Ikan-ikan tidak mendatangi pantai mereka pada hari-hari lain dalam seminggu, sementara pada hari Sabtu ikan-ikan itu datang (syurra’an), yaitu berbondong-bondong di tepi laut, terus berdatangan di depan mata mereka. Kemaksiatan terjadi pada mereka dengan menangkap ikan pada hari Sabtu, setelah Allah mengharamkannya atas mereka, sehingga terbentuklah Umat yang bermaksiat dan melampaui batas. Di sini, orang-orang lain terbagi menjadi dua: Satu kelompok berkata, “Kita harus memerintah mereka kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran”; dan kelompok lain berkata, “Tidak ada gunanya, azab pasti akan menimpa mereka, dan keadaan mereka tidak akan membaik sebelum itu.”
Dengan demikian, kita memiliki tiga kelompok: Kelompok yang melanggar batas; Kelompok yang menasihati; dan Kelompok yang diam. Di sini Allah Ta’ala berfirman:
(Dan tanyakanlah kepada mereka tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air pada hari Sabat, dan pada hari-hari yang bukan Sabat, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Dan (ingatlah) ketika suatu umat di antara mereka berkata, “Mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab oleh Allah dengan azab yang keras?” Mereka menjawab, “Agar kami mempunyai alasan (lepas dari tanggung jawab) di hadapan Tuhanmu, dan agar mereka bertakwa.” Maka ketika mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, Kami selamatkan orang-orang yang melarang (mereka) berbuat kejahatan dan Kami siksa orang-orang yang zalim dengan siksaan yang pedih, karena mereka selalu berbuat fasik.) (QS Al-A’raf: 163-165). Ini berarti bahwa Umat yang menasihati telah mengingatkan mereka, lalu mereka melupakan dan mengabaikan apa yang diperingatkan kepada mereka, dan Kami selamatkan khusus orang-orang yang melarang dari kejahatan.
Pertanyaannya: Ke mana perginya (Umat yang diam)? Sebagian riwayat mengatakan: Mereka pergi bersama orang-orang yang sesat dengan azab yang pedih; karena Umat yang menasihati mendapatkan alasan (‘udzr), tetapi Umat yang diam tidak mendapatkan alasan, sehingga azab kaum itu menimpa mereka:
(Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang, Kami katakan kepada mereka, “Jadilah kamu kera yang hina.”) (QS Al-A’raf: 166).
Kisah ini memberikan kita pelajaran bahwa Amar Makruf dan Nahi Mungkar adalah kewajiban, meskipun kemungkinan kecil Umat ini mendapat hidayah. Meninggalkan Amar Makruf—walaupun dengan kemungkinan pengaruh yang kecil—termasuk dosa besar; berdasarkan tafsiran dosa besar sebagai sesuatu yang diancam oleh Allah dengan azab dalam Alquran.
Yang kami tuju adalah bahwa tidak benar membesar-besarkan gagasan kemungkinan pengaruh, sehingga kita menciptakan alasan bagi diri kita sendiri untuk melepaskan tanggung jawab kita. Oleh karena itu, kita menemukan bahwa sebagian ahli fikih berbicara tentang cukupnya kemungkinan pengaruh, meskipun di masa depan, dengan asumsi pengulangan perintah dan larangan, meskipun untuk waktu yang tidak sebentar (Lihat—sebagai contoh—: Al-Khomeini, Tahriir al-Wasiilah 1: 468; dan Fadlullah, Fiqh asy-Syari’ah 1: 627-628).
Bahkan, boleh jadi seorang pengilham mengilhami dari kisah ini bahwa keberadaan fenomena Amar Makruf adalah salah satu faktor penyelamat dari azab, dan bahwa ketiadaannya dapat membuat azab menimpa bahkan orang-orang beriman yang saleh.
Hal ini mungkin juga diilhami dari Surah Al-Ashr, di mana Allah Ta’ala berfirman:
(Demi masa. Sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.) (QS Al-Ashr: 1-3). Mereka yang keluar dari lingkaran kerugian adalah mereka yang memiliki tiga sifat: a) Iman; b) Amal Saleh; c) Saling menasihati (Tawashau) dalam kebenaran dan kesabaran, yang berarti saling mengajak kepada iman, kesabaran, dan kebajikan.
Permasalahan Ketujuh: Kebekuan pada Kemungkaran Individual
Salah satu isu yang mendominasi literatur kita adalah bahwa kemungkaran adalah perilaku individual yang dapat kita hadapi dalam kehidupan. Biasanya kita tidak menyadari bahwa kewajiban Amar Makruf dan Nahi Mungkar juga memiliki sisi-sisi umum (non-perilaku). Ia memiliki sisi sosial, sisi politik, memerangi kezaliman dan tirani, memerangi kelas-kelas yang tersebar di kalangan umat Islam, termasuk di antara orang-orang yang beriman, saleh, dan taat, serta memerangi korupsi keuangan, administrasi, kelas, korupsi moral, dan lain-lain. Namun, ada sisi penting dalam kewajiban ini yang kita abaikan kebutuhannya, yaitu sisi intelektual dan budaya.
Banyak dari kita membayangkan bahwa kewajiban ini adalah upaya untuk mengubah kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang, padahal konsep seruan kepada kebaikan, membimbing orang yang tidak tahu (irshadul jahil), dan Amar Makruf dan Nahi Mungkar adalah konsep yang mencakup hingga menarik perhatian orang lain terhadap penyimpangan intelektual dan budaya yang mereka alami.
Para ahli fikih membedakan antara gagasan Amar Makruf dan membimbing orang yang tidak tahu, di mana mereka berkata: Jika seseorang melakukan perbuatan yang tidak benar, tetapi ia tidak tahu bahwa itu salah, maka tugas kita terhadapnya adalah (membimbing orang yang tidak tahu). Namun, jika ia melakukannya sambil mengetahui bahwa itu salah, maka tugas kita terhadapnya adalah (Amar Makruf dan Nahi Mungkar). Di sini, kita tidak berbicara dalam konsep fikih, tetapi kita berbicara tentang Amar Makruf dalam makna luasnya:
(Menyeru kepada kebaikan, memerintah kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar…) (QS Ali Imran: 104), yaitu dalam makna umum. Di sini, tidak ada bedanya antara menjauhkan seseorang dari perbuatan haram yang ia ketahui haram, dengan menjelaskan kepadanya kebenaran dari kebatilan. Sesungguhnya tugas besar para Nabi adalah menghadapi penyimpangan akidah, budaya, dan intelektual melalui hal-hal seperti Tauhid, Hari Kebangkitan, Kenabian, dan lain-lain.
Kita sering mengira bahwa dialog intelektual, budaya, dan akidah bukanlah bagian dari proses Amar Makruf, padahal yang benar adalah ia termasuk dalam konteksnya dan tidak terpisah darinya. Menurut saya, setiap kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memperbaiki pikiran dan konsep pada akhirnya bermuara pada judul seruan kepada kebaikan dan Amar Makruf dan Nahi Mungkar. Amar Makruf bukan hanya memperbaiki individu dalam kemungkaran perilaku yang ia lakukan dengan kesadaran, tetapi juga memperbaiki budaya, kesadaran, dan ide-ide masyarakat.
Sebagian pemikir kontemporer, seperti Dr. Hassan Hanafi, berpendapat bahwa Amar Makruf dan Nahi Mungkar tidak boleh kita masukkan ke dalam dunia konsep dan ide, dan bahwa keduanya adalah masalah sosial; karena jika kita memaksakan gagasan Amar Makruf ke dalam isu-isu pemikiran, budaya, dan perselisihan ilmiah, hal itu akan menyebabkan penghapusan kebebasan. Setiap orang yang berbeda pendapat dengan orang lain harus menindasnya dan menyita kebebasannya; karena ia percaya bahwa ia sedang memerintahnya kepada kebaikan dan mencegahnya dari kemungkaran. Dan ini akan menyebabkan tertutupnya pintu ijtihad dalam fikih, sejarah, teologi (kalam), filsafat, ilmu tafsir, hadis, ushul, rijal, dan ilmu humaniora lainnya (Lihat: Hanafi, Min al-’Aqidah ilaa ath-Thawrah 5: 257-258). Oleh karena itu, kewajiban ini harus dinetralkan dari dunia pemikiran; karena itu adalah dunia terbuka yang tidak ada hubungannya dengan Amar Makruf, dan tidak boleh melarang ide-ide dengan dalih Amar Makruf. Ide ini diilustrasikan oleh Dr. Hassan Hanafi dengan sejarah Islam, di mana ia menganggap bahwa Mu’tazilah telah melakukan kesalahan di sini. Kita semua tahu bahwa Mu’tazilah adalah salah satu kelompok yang menyerukan kebebasan, logika, akal, dan pemikiran, serta meyakini kehendak dan pilihan manusia. Mu’tazilah mengalami pemenjaraan, penindasan, pengepungan, dan penyiksaan, sampai Allah memberikan salah satu khalifah Abbasiyah untuk bersama mereka. Ketika Negara Abbasiyah meyakini pemikiran Mu’tazilah, semua hakim, mufti, ulama, dan semua yang mempelajari teologi (kalam) dan debat di Baghdad dan tempat lain berada di bawah belas kasihan Mu’tazilah, dan mazhab mereka menyaksikan kebangkitan besar di abad ketiga Hijriah.
Namun, kesalahan yang dilakukan Mu’tazilah—dari sudut pandang orang-orang yang mengatakan kenetralan Amar Makruf dari dunia pemikiran—adalah bahwa ketika mereka menjadikan Amar Makruf dan Nahi Mungkar sebagai salah satu prinsip agama (Ushul ad-Din), mereka mengatakan bahwa perbaikan ide-ide adalah salah satu ciri terpenting Amar Makruf dan Nahi Mungkar. Dengan ini, mereka membenarkan diri mereka sendiri untuk menghantam dengan tangan besi setiap orang yang berbeda pendapat dengan mereka, sehingga mereka membunuh semua orang yang menentang mereka, memenjarakan mereka, dan terjadi tragedi dalam sejarah Islam selama periode itu. Situasi ini berlanjut hingga Allah memberikan kepada Ahlul Hadits seorang khalifah Abbasiyah lain setelah itu, yang menggunakan perlakuan yang sama terhadap Mu’tazilah seperti yang digunakan Mu’tazilah terhadap lawan-lawannya, sehingga menghancurkan mereka. Sejak abad keempat Hijriah hingga awal abad keempat belas Hijriah, Mu’tazilah berakhir dalam sejarah Muslim; mereka dibunuh, diusir, buku-buku mereka dibakar, dan mereka tidak diizinkan berbicara.
Jika kita merenungkan sudut pandang ini—yaitu tidak memasukkan Amar Makruf ke dalam dunia pemikiran—kita akan menemukan bahwa sumber kekhawatiran utamanya adalah penindasan (al-qam’u). Dalam istilah fikih, itu adalah tingkat ketiga dari tingkatan Amar Makruf dan Nahi Mungkar (tingkat Tangan). Amar Makruf memiliki tiga tingkatan: 1. Tingkat Hati; 2. Tingkat Lisan; 3. Tingkat Tangan.
Jika Amar Makruf dan Nahi Mungkar dengan ketiga tingkatannya dipaksakan ke dalam bab perbaikan intelektual, dan dalam bab konfrontasi akidah dan budaya, hal itu akan mengarah pada penindasan, pemukulan, penyiksaan, kekerasan, dan penyitaan kebebasan.
Jadi, sumber kekhawatiran adalah (penindasan). Inilah yang membedakan antara era penindasan Mu’tazilah dan Ahlul Hadits dengan era Bani Buwaih yang mengizinkan para pemikir dari semua mazhab dan aliran Islam untuk memiliki pendapat, menerbitkan buku-buku mereka, memiliki mimbar (kursi) untuk kalam di Baghdad, dan menyaksikan debat di istana. Oleh karena itu, abad di mana Bani Buwaih memerintah, dari tahun (320 H) hingga tahun (447 H)—saat jatuhnya Baghdad di tangan Seljuk—dikenal sebagai (Masa Keemasan Islam), bahkan atas pengakuan para orientalis, di mana dari segi intelektual kita menemukan munculnya sebagian besar karya dan ilmu-ilmu Islam pada abad ini, berbeda dengan abad sebelumnya, di mana Ahlul Hadits dan Mu’tazilah melakukan apa yang mereka lakukan.
Maka, masalahnya bukanlah pada prinsip Amar Makruf, sebagai dialog intelektual untuk meyakinkan orang lain tentang apa yang saya anggap benar, tepat, dan aman, melainkan terletak pada tingkat ketiga dari tingkatannya, jika kita memaksakannya ke dalam Amar Makruf, maka perselisihan intelektual akan membawa kita pada penindasan timbal balik, dan barang siapa yang memiliki kekuatan akan dianggap benar berdasarkan persamaan ini.
Oleh karena itu, saya ingin masuk ke Permasalahan Kedelapan untuk mengatasi masalah ini, yaitu gagasan kekerasan dalam Amar Makruf dan Nahi Mungkar: Apakah kekerasan disyariatkan dalam konteks ini pada dasarnya—baik dalam pemikiran atau lainnya—atau tidak?
Permasalahan Kedelapan: Masalah Kekerasan dalam Amar Makruf dan Nahi Mungkar
Menerangi permasalahan ini, dan memberikan jawaban yang terhubung dengannya, akan membantu kita menyelesaikan permasalahan sebelumnya, dan dengan demikian, kerja intelektual dalam bab Amar Makruf akan menjadi sah dan disyariatkan.
Para ahli fikih telah berbicara selama berabad-abad bahwa tingkatan Amar Makruf ada tiga, yaitu: (Hati, Lisan, Tangan).
Adapun tingkat Hati, ia memiliki dua makna: Salah satunya tidak berhubungan dengan Amar Makruf; dan yang kedua memiliki kaitan erat dengannya.
Makna tingkat Hati dalam penafsiran yang pertama adalah ketidakrelaan—secara psikologis dan emosional—terhadap kemungkaran. Hal ini wajib, tetapi bukan Amar Makruf; karena saya tidak memerintah siapa pun. Para ahli fikih muta’akhirin (belakangan) mengatakan: Ini adalah salah satu kewajiban yang ditunjukkan oleh dalil. Jika saya melihat kemungkaran di suatu tempat, saya harus mengingkarinya di dalam hati saya, artinya saya harus mendidik diri saya secara moral sehingga mendengar kemungkaran menimbulkan semacam tekanan psikologis, kebencian, dan ketidaknyamanan. Saya, dalam diri saya, mencintai ma’ruf dan merasa bahagia dengan kehadirannya, dan tidak merelakan kemungkaran. Inilah pendidikan interaksi positif dengan ma’ruf dan interaksi negatif dengan munkar. Ini adalah kewajiban pada dasarnya, tetapi tidak ada hubungannya dengan Amar Makruf (memerintah kepada kebaikan).
Adapun tingkat Hati yang berhubungan dengan Amar Makruf adalah yang mereka gambarkan sebagai setiap reaksi eksternal yang dilakukan seseorang terhadap suatu kemungkaran, yang tidak melibatkan Lisan atau Tangan, seperti: mengerutkan dahi di hadapan pelaku kemungkaran, mengalihkan pandangan darinya, atau menunjukkan ketidaknyamanan darinya. Artinya, itu adalah setiap metode non-lisan dan tidak menggunakan kekerasan. Inilah yang disebut tingkat Hati di sini, sementara setiap metode yang menggunakan Lisan (pernyataan verbal) disebut tingkat Lisan.
Oleh karena itu, banyak ahli fikih muta’akhirin berkata: Tidak ada perbedaan antara tingkat Hati dan Lisan, karena keduanya adalah segala bentuk ekspresi non-kekerasan. Lisan berarti penjelasan (bayan): saya menjelaskan kepadanya dengan ekspresi wajah saya, atau berpaling darinya, atau tidak menanggapi permintaannya; atau saya menjelaskan kepadanya dengan lisan dan kata-kata. Oleh karena itu, sebagian ahli fikih mengatakan bahwa tingkat Hati dan Lisan adalah satu (Lihat: Al-Khoei, Minhaj ash-Shalihin 1: 352-353). Bahkan, jika kita bersikeras memisahkannya, maka Hati adalah setiap sarana ekspresif yang tidak melibatkan Lisan dan Tangan, dan Lisan adalah setiap sarana ekspresif yang menggunakan lisan dan pernyataan verbal untuk menjelaskan masalah kepada pihak lain, baik berupa perintah maupun larangan.
Adapun tingkat Tangan (Tingkat Ketiga), ada perdebatan di kalangan ulama tentang makna (Tangan). Ada lebih dari satu penafsiran di sini, kita sebutkan beberapa di antaranya:
Penafsiran Pertama: Apa yang dianut oleh mayoritas ulama bahwa makna (Tangan) adalah Kekerasan (al-’Unf). Ini tidak selalu buruk; semua undang-undang di dunia menggunakan kekerasan (seperti penjara, misalnya). Kekerasan di sini dapat berupa pemukulan, penjara, penahanan, penyitaan harta, perusakan harta, disposisi harta, atau lainnya. Bahkan ada yang berpendapat bahwa itu mencakup hingga melukai, mematahkan beberapa anggota tubuh, atau memotongnya. Bahkan ada yang berpendapat di sini bahwa tidak ada dalil untuk mengaitkan penerapan tingkat ini dengan izin penguasa syar’i (hakim syar’i) atau aparat negara yang sah, meskipun ada pendapat lain yang mengaitkannya—terutama dalam hal seperti melukai dan mematahkan—dengan izin ini.
Banyak ulama—Sunni maupun Syiah—yang meyakini penafsiran ini secara prinsip, tetapi sekelompok ulama muta’akhirin meninjau kembali masalah ini, dan berkata: Tingkat Tangan—dengan makna dan penafsiran ini—tidak ada dalilnya. Di antara ulama yang menolak tingkat ini adalah Sayyid Mahmoud al-Hashemi, Mirza Jawad at-Tabrizi, Sayyid Taqi al-Qummi, dan Al-Muhaqqiq al-Ardabili, yang mengatakan—maksud saya Al-Ardabili—, “Jika bukan karena ijmak, tidak ada dalil untuk tingkat ini” (Lihat: Majma’ al-Faidah wal Burhan 7: 543). Dia bermaksud bahwa tidak ada ayat mulia atau hadis mulia yang pasti sanad dan maknanya yang dapat menunjukkan penetapan tingkat ini dalam Amar Makruf dan Nahi Mungkar.
Penafsiran Kedua: Makna (Tangan) adalah pengerahan pengaruh untuk mencegah terjadinya keharaman. Misalnya: Jika ada partai politik Islam yang melakukan intervensi untuk mengeluarkan undang-undang di parlemen, misalnya, untuk membatasi minum minuman keras, maka di sini ia mengerahkan tingkat Tangan, dalam arti ia mengerahkan pengaruhnya—tanpa kekerasan langsung terhadap siapa pun—agar menghalangi orang dari kemaksiatan.
Jadi, Tangan di sini adalah praktik praktis yang bekerja untuk mencapai pencegahan antara pelaku maksiat dan perbuatan maksiat di masyarakat, tanpa menggunakan kekerasan dalam makna yang umum.
Penafsiran Ketiga: Ini adalah pandangan salah satu ulama kuno kita, yaitu Sallar ad-Dailami, penulis kitab (Al-Marasim al-’Alawiyyah), di mana ia berkata bahwa Tangan dalam Amar Makruf dan Nahi Mungkar berarti orang yang memerintah kepada kebaikan melakukan kebaikan agar orang lain meneladaninya (Al-Marasim al-’Alawiyyah: 263). Konsep di sini berlawanan total dengan apa yang ada dalam benak kita. Amar Makruf dengan Tangan di sini berarti dengan perbuatan. Misalnya, Anda memiliki kedudukan spiritual di antara masyarakat, lalu Anda salat berjamaah di masjid, maka orang-orang meneladani Anda dan bergerak untuk salat berjamaah di masjid. Ini adalah Amar Makruf, tetapi itu adalah perintah praktis, bukan perkataan, dan bukan sekadar menunjukkan kebencian, tanpa—pada saat yang sama—mencapai penggunaan kekerasan.
Di antara ketiga penafsiran ini, kita ingin berhenti sebentar pada Penafsiran Pertama. Mereka yang mengatakan kekerasan fisik memiliki banyak dalil, yang paling menonjol adalah dua dalil:
Dalil Pertama: Keumuman ayat-ayat Alquran dan riwayat, di mana mereka mengatakan, “Wajib atas kalian untuk Amar Makruf dan Nahi Mungkar”. Itu tidak dibatasi, melainkan mutlak, dan tidak membatasinya pada Tangan atau menunjukkan kebencian di wajah, melainkan dengan cara apa pun Anda mencegah orang lain dari kemungkaran. Ini berarti tidak ada pembatasan pada mekanisme, sarana, atau metode, melainkan urusan ada di tangan saya, yang penting tujuan tercapai. Ya, di sini muncul dalam fikih hukum yang kita sebut (Hukum yang Paling Mudah), artinya yang paling ringan ke yang paling ringan (dari bawah ke atas). Jika semua cara tidak berhasil, dan hanya kekerasan yang tersisa, maka kita menggunakan kekerasan dalam situasi ini.
Para kritikus yang menolak gagasan kekerasan fisik dapat mengatakan di sini: Tidak mungkin berdalil dengan nas-nas yang mutlak; karena Allah ‘Azza wa Jalla, ketika memerintahkan kita dengan sesuatu, Dia memerintahkan kita untuk menggunakan semua sarana selama sarana itu sendiri tidak diharamkan. Misalnya: Jika teks mengatakan kepada saya, “Masukkan kebahagiaan ke dalam hati saudaramu yang beriman,” jika orang tersebut merasa bahagia dengan menggunjing orang lain, apakah boleh kita menggunjing mereka untuk memasukkan kebahagiaan ke dalam hatinya?! Tentu saja tidak, meskipun riwayatnya mutlak. Bahkan, dalil-dalil kewajiban dipalingkan dari hal-hal yang diharamkan. Artinya, ketika Allah memerintahkan saya dengan suatu kewajiban, saya dapat menggunakan sarana apa pun untuk mencapai kewajiban tersebut selama sarana itu sendiri bukan dari hal-hal yang diharamkan (pada dirinya sendiri di sisi Allah Ta’ala); karena Allah tidak ditaati melalui jalan maksiat, jika tidak, kita harus melakukan semua hal yang diharamkan dengan memperdaya Allah.
Akibatnya adalah bahwa ayat-ayat dan riwayat memerintahkan prinsipnya, dan tidak menentukan caranya. Maka, detail dan penggunaan kekerasan atau tidak menggunakannya didiamkan dalam teks.
Dalil Kedua: Ini adalah dalil yang paling kuat di sini, yang saya maksud adalah hadis-hadis yang mencapai sekitar lima belas riwayat yang telah diteliti oleh para ahli fikih di tempatnya, di antaranya: Riwayat yang terkenal: (“Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan Tangan-nya…”). Bahkan riwayat ini secara khusus ada di sumber-sumber Sunni dan Syiah sekaligus, dan dapat dikatakan hampir disepakati di kalangan Muslim. Riwayat-riwayat ini jelas, ia telah menentukan jalan bagi kita, dan membenarkan kekerasan.
Para ulama kritikus dapat mengatakan di sini juga: Mayoritas riwayat dipertanyakan dari segi sanad dan sumber. Penelitian ini tidak ada hubungannya dengan kita saat ini, tetapi mari kita berhenti sebentar pada hadis yang terkenal yang tertanam kuat di benak kita semua: (“Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan Tangan-nya, jika ia tidak mampu maka dengan Lisan-nya, dan jika ia tidak mampu maka dengan Hati-nya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman”) (Shahih Muslim 1: 50). Tidak mungkin yang dimaksud dengan (Tangan) dalam hadis ini adalah kekerasan; karena ini berarti bahwa jika saya melihat seseorang melakukan maksiat di depan saya, saya harus langsung memukulnya, jika ia tidak yakin dengan pemukulan, baru saya berbicara dengannya. Ini tidak logis, bahkan berlawanan dengan fatwa para ahli fikih. Oleh karena itu, Sallar ad-Dailami berkata: Karena riwayat dimulai dengan Tangan, maka yang dimaksud dengan Tangan adalah Anda melakukan ma’ruf.
Dari sini, para kritikus mengajukan bahwa riwayat ini tidak jelas dalam masalah kekerasan; karena bertentangan dengan sistem yang dijadikan dalil dalam fikih, yaitu sistem (yang paling mudah), yaitu pergi dari yang terendah ke yang tertinggi. Ditambah lagi, riwayat ini dalam sumber-sumber Syiah sanadnya lemah yang tidak dijadikan sandaran oleh banyak ulama, bahkan ia termuat dalam beberapa kitab yang tidak diakui di kalangan mereka. Saya telah mempelajari berbagai dalil dan riwayat ini secara terperinci dalam buku sederhana saya (Fiqh al-Amr bil Ma’ruf wan Nahy ‘anil Munkar: 470-516).
Dari sini, muncul kehati-hatian umum terhadap dalil-dalil kekerasan dalam Amar Makruf. Namun, pertanyaannya adalah: Bagaimana para penolak tingkat ini dapat memahami masalahnya?
Sebagai penolak penggunaan sarana kekerasan, kita menganalisis Amar Makruf dalam kerangka umum, di mana terdapat dua konsep untuk Amar Makruf: Umum dan Khusus.
Konsep Umum Amar Makruf adalah setiap sarana yang berupaya untuk menerapkan Agama; agar Kebenaran dan Ma’ruf terwujud; dan agar Kemungkaran tidak terjadi. Jika demikian, maka Tangan, jika kita ingin menafsirkannya sebagai kekerasan, maknanya menjadi seperti (Peradilan); karena hakim menggunakan kekuasaan, sehingga Tangan dalam makna umum menjadi hukuman balasan (qishash), undang-undang pidana, hukum hudud, diyat (denda), dan sejenisnya. Dan (Tangan) dalam Amar Makruf dan Nahi Mungkar juga menjadi Jihad, dan seterusnya.
Jadi, jika kita mengambil makna umum Amar Makruf, kita akan memiliki: tingkat Hati, tingkat Lisan (mengajak orang kepada Kebenaran), dan tingkat (Kekuatan), yang dimaksud adalah kekuatan dalam saluran hukumnya, misalnya: dalam syarat-syarat hudud, syarat-syarat jihad, syarat-syarat qishash, dan seterusnya. Maka, (Tangan) berarti berusaha menegakkan Syariat Islam dalam tingkatan yang berbeda-beda. Artinya, saya berusaha menegakkan Syariat tanpa memaksa siapa pun. Jika saya tidak mampu, barulah saya berbicara dengan orang-orang dan mengajak mereka. Jika kita dapat mewujudkan Syariat dalam kehidupan secara alami, maka tujuan telah tercapai. Tetapi jika kita tidak mampu, kita harus meyakinkan orang-orang untuk menjadikan Syariat sebagai hukum kehidupan mereka, agar mereka berkomitmen pada Agama, dan melakukan ma’ruf… Dengan ini, konsepsi kita tentang (Tangan) berbeda secara radikal dari semua orang, termasuk Sallar ad-Dailami.
Adapun Konsep Khusus Amar Makruf, yang merupakan urusan yang berbeda dari jihad, qishash, peradilan, dan lain-lain, maka kekuatan kekerasan sama sekali bukan bagian darinya, kecuali dalam batas-batas yang sangat istimewa dan luar biasa.
Jika kita mengadopsi sudut pandang ini, tidak akan ada masalah dalam kebebasan berpikir; karena perbedaan pendapat dengan penyimpangan intelektual akan menjadi perbedaan pendapat intelektual, melalui penerbitan buku, ceramah, penggunaan media, atau kegiatan sosial untuk menentangnya, selama pihak lain tidak melakukan kejahatan hukum, seperti pembunuhan atau perzinahan. Jika ia melakukannya, ia harus dihukum sesuai dengan Syariat, dalam batas-batas dan syarat-syarat objektif untuk itu. Dengan ini, hilanglah pembenaran kekhawatiran yang mendorong orang-orang seperti Dr. Hassan Hanafi untuk berhati-hati agar kewajiban ini tidak meluas ke ranah pemikiran, pengetahuan, dan budaya. Sebaliknya, Amar dan Nahy di sini menjadi efektif, tanpa mengarah pada kekhawatiran yang diungkapkan oleh orang-orang seperti Hassan Hanafi, seperti: tertutupnya pintu ijtihad, dan penindasan terhadap ahli fikih dan ulama.
Permasalahan Kesembilan: Hilangnya Fikih Prioritas
Teori Fikih Prioritas (Fiqh al-Awlawiyyat) ada dalam ilmu Ushul al-Fiqh (Prinsip-prinsip Fikih), tetapi dalam bentuk yang sederhana. Salah satu yang paling menyorotinya dan memberinya kepentingan adalah Syekh Murtadha Mutahhari, yang mengatakan bahwa Fikih Prioritas seperti termometer dalam tubuh. Jika termometer rusak, anggota tubuh akan terganggu, dan yang didahulukan menjadi diakhirkan, yang diakhirkan menjadi didahulukan, yang penting menjadi tidak penting, dan yang tidak penting menjadi penting.
Mutahhari memberikan contoh, yaitu seseorang yang keluar dari Teheran untuk mengunjungi Imam Husain di Karbala. Ia dihentikan di perbatasan; mereka menanyainya, lalu ia berbohong; misalnya karena ia memiliki masalah tertentu. Di sini, ia telah melakukan haram, yaitu kebohongan; demi sunnah/mustahab, yaitu ziarah.
Ini adalah contoh sederhana. Kita sering jatuh ke dalam hal seperti ini tanpa kita sadari; karena kita tidak memperhatikan peta hierarki prioritas.
Dengan ini, Mutahhari menyimpulkan bahwa tidak boleh saya melakukan hal yang diharamkan demi melakukan hal yang sunnah (mustahab), meskipun itu sangat ditekankan.
Ketika teori Fikih Prioritas hilang dari Amar Makruf—pada tingkat sosial umum—maka mungkin saja orang-orang yang melakukan Amar Makruf dan Nahi Mungkar memenuhi seluruh area dengan topik sepele—yang ia anggap penting—dan meninggalkan puluhan prioritas lain yang ia tidak tahu bahwa itu lebih penting daripada topik yang sedang ia kerjakan.
Hal ini adalah salah satu masalah mendasar dalam aktivitas orang-orang yang bekerja di bidang intelektual, budaya, dakwah, tabligh, dan keimanan.
Agar kita memiliki akal prioritas, kita harus mengetahui waktu, tempat, dan apa yang diinginkan oleh Teks (wahyu); di mana Teks dan Realitas merupakan dualitas: Apa yang Teks inginkan dari saya? Dan apa yang dapat ditanggung atau dibutuhkan oleh Realitas? Dengan ini, saya menggabungkan antara Teks dan Realitas, seperti yang diserukan oleh Sayyid Muhammad Baqir as-Sadr. Saya harus memahami realitas untuk menghukumi Teks di dalamnya, alih-alih menghukumi Teks dalam kekosongan, dan saya harus mengetahui realitas agar saya menerapkan nilai-nilai di dalamnya, jika tidak, saya akan menyia-nyiakan nilai-nilai, dan mengorbankan ide-ide, padahal saya mengira saya sedang melayaninya.
Fikih Prioritas sangat penting dalam dunia tabligh dan dakwah, tidak hanya dalam Amar Makruf; melainkan penting dalam segala hal.
Siapa pun yang kehilangan Fikih Prioritas akan kehilangan kesadaran akan waktu, tempat, dan segalanya, dan ilmunya akan sia-sia, bukan di dalam dirinya sendiri, tetapi dalam penerapan ilmunya di luar; keseimbangan akan terganggu di sisinya, sehingga ia melihat ini lebih penting lalu ia mengerjakannya, padahal yang lebih penting secara riil terlewatkan, sehingga ia menyibukkan area dengan yang lebih sedikit, padahal seharusnya ia menyibukkannya dengan yang lebih banyak.
Jadi, kita harus memahami tuntutan dan prioritas, dan di tahap waktu manakah kita hidup? Apakah prinsip-prinsip utama yang seharusnya kita kerjakan sekarang? Dan apakah urusan-urusan cabang yang ingin kita berikan haknya juga? Bagaimana kita menyeimbangkan? Dan bagaimana kita membedakan?
Masalah-masalah ini terabaikan oleh banyak orang. Bahkan menurut pendapat saya yang rendah hati, poin ini timbul dari ketidakpahaman dan ketidak-telaahan kita terhadap sirah (sejarah hidup Nabi/Imam) secara analitis. Sirah para Nabi, Imam, dan Sahabat selalu kita pelajari secara individual, dan menurut istilah para sejarawan (dirasah hauwliyyah), yaitu sesuai urutan waktu, tetapi kita jarang melihat—kecuali pada ulama muta’akhirin, alhamdulillah—sirah yang analitis, seperti: Apa tujuannya? Apa rencana strategis yang ditetapkan para Imam? Apa prioritas yang mereka pegang? Bagaimana mereka mengorbankan yang kurang bernilai demi yang lebih bernilai? Bagaimana mereka menyeimbangkan antara maslahat (kebaikan) dan mafsadat (kerusakan)? Padahal, maslahat di sini adalah maslahat nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan Agama. Inilah yang kita butuhkan hari ini. Hilangnya Fikih Prioritas dari orang yang bekerja di bidang tabligh dan dakwah dapat mengarah—bahkan telah mengarah di beberapa tempat—pada bencana bagi dirinya sendiri, masyarakat di sekitarnya, bahkan bagi nilai-nilainya sendiri.
Fikih Prioritas dimulai dari kesadaran akan realitas dengan waktu dan tempatnya terlebih dahulu; dan kedua dengan memperhadapkan realitas ini pada Teks, untuk mengetahui apa yang diinginkan? Dan apa yang diminta? Dari sini, perlu disiapkan lokakarya kualifikasi bagi semua yang bekerja di bidang tabligh, dan semua yang bekerja di bidang Amar Makruf; agar mereka memahami realitas. Jika saya ingin pergi ke suatu negara untuk tabligh, saya harus tahu negara ini, apa masalahnya? Apa sisi positifnya? Apa sisi negatifnya? Apa sifat-sifat orang di dalamnya? Jika saya ingin memberikan ceramah kepada sekelompok orang, saya harus bertanya: Apa topik terbaik bagi mereka? Dan apa yang marjinal? Saya mungkin salah, saya mungkin benar, tetapi saya harus berpikir dengan cara ini.
Hari ini, salah satu prioritas terpenting bagi orang-orang yang melakukan Amar Makruf dan Nahi Mungkar adalah mekanisme pembaruan, yaitu mengikuti semua perkembangan baru yang terjadi dari permasalahan yang beraneka ragam warnanya. Oleh karena itu, kita harus mendistribusikan peran; sebagian dari kita mengerjakan permasalahan yang datang dari pihak (A), dan sebagian dari kita mengerjakan permasalahan yang datang dari pihak (B), dan seterusnya. Kita harus mendistribusikan peran, dan membuat rencana strategis dari posisi bertindak, bukan dari posisi bereaksi. Inilah makna bahwa Fikih Prioritas memaksakan pembaruan. Penting bagi kita untuk memiliki prioritas pembaruan dan komunikasi, bukan prioritas menjauh dan berpisah, dan prioritas bekerja pada kritik diri; agar kita meruntuhkan kekurangan dalam diri kita; demi membangun diri kita.
Dan kami percaya pada prioritas yang sangat besar hari ini di tahap kita, yang dengannya saya akhiri pembicaraan saya, yaitu: Prioritas Nilai-nilai Moral dan Spiritual.
Penutup Mengenai Prioritas Nilai-nilai Spiritual dan Moral
Telah tertanam dalam benak kita bahwa Agama adalah soal halal dan haram (Fikih), padahal Fikih memiliki dua sisi: sisi lahiriah, yaitu hal-hal yang bersifat formal, seperti cara berwudu, tayamum, salat, dan puasa; dan sisi moral dan spiritual, yang lebih dalam dari yang pertama. Sayangnya, kita lebih mementingkan aspek formal daripada spiritual dan moral. Oleh karena itu, ketika kita menilai apakah seseorang itu religius atau tidak, kita melihat pada aspek formalnya: apakah ia berjanggut—misalnya—atau tidak? Jika ia mencukur janggut, maka ia tidak religius!! Sementara jika ia menggunjing orang lain selama sepuluh jam di depan saya, ia tetap dianggap religius, meskipun ia bergunjing!! Padahal, ghibah (menggunjing) adalah maksiat yang lebih besar daripada mencukur janggut.
Kita meyakini masalah lahiriah dan formal, tetapi tidak seharusnya kita terpaku padanya. Inilah yang selalu diserukan oleh para ahli etika (akhlakiyyun), ahli makrifat (‘urafa’), dan orang-orang dengan kecenderungan spiritual. Lahiriah Agama adalah Fikih, dan Fikih adalah sarana bagi nilai-nilai spiritual untuk turun ke dalam hati kita. Allah Ta’ala berfirman:
(…dan dirikanlah salat untuk mengingat-Ku) (QS Thaha: 14). Yang dimaksud adalah mengingat-Nya di dalam hati, bukan hanya gerakan lisan semata. Demikian juga firman-Nya:
(Daging (hewan kurban) dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada-Nya adalah ketakwaan dari kamu…) (QS Al-Hajj: 37).
Jika seseorang menyembelih unta atau hadyu (hewan kurban haji) di Mina, daging-daging ini tidak akan sampai kepada Allah. Yang penting adalah keadaan spiritual yang telah kita jauhi; karena terkadang kita terpaku pada hal-hal lahiriah dan formal, padahal hal-hal formal itu penting, tetapi tidak boleh membatasinya saja, yang menyebabkan hilangnya pesan spiritual.
Bahkan dalam Tauhid (Keesaan Tuhan), banyak Muslim hari ini memiliki masalah. Kita membayangkan bahwa keesaan Allah Subhanahu wa Ta’ala adalah pertempuran angka—seperti yang saya sebut—: Apakah Allah satu, dua, atau tiga? Apakah pertempurannya benar-benar di sini?! Apakah Allah mengutus semua nabi dan rasul, dan terjadi semua pertempuran ini dengan musuh-musuh mereka; hanya untuk bertempur demi angka (satu), bukan (dua)? Masalahnya tidak demikian. Seluruh fokus pada Tauhid ini adalah karena masalah orang-orang Arab bukanlah apakah Allah Sang Pencipta Wajibul Wujud itu satu. Mereka percaya bahwa yang menciptakan alam semesta itu satu, dan Alquran sendiri mengatakan demikian:
(Dan sungguh, jika engkau tanyakan kepada mereka, “Siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan?” Pasti mereka akan menjawab, “Allah.” Maka mengapa mereka bisa dipalingkan (dari kebenaran)?) (QS Al-’Ankabut: 61).
(Katakanlah, “Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan?” Maka mereka akan menjawab, “Allah.” Maka katakanlah, “Mengapa kamu tidak bertakwa (kepada-Nya)?” Maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya; maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu dipalingkan?) (QS Yunus: 31-32).
Mereka mengetahui pemahaman teoretis tentang keesaan Allah, tetapi keesaan emosional terhadap Allah tidak ada. Sebaliknya, yang hadir dalam kehidupan sehari-hari mereka adalah berhala; kepada berhala mereka berlindung dan berharap, darinya mereka takut, dan untuknya persembahan diberikan, dan lain-lain.
Allah Subhanahu wa Ta’ala tidak hadir dalam kehidupan kita. Meskipun kata yang paling sering diulang dalam Alquran, beserta sifat-sifatnya, adalah kata (Allah), kita tidak merasakan kehadiran spiritual Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam jiwa kita! Seluruh sistem keagamaan adalah Tauhid. Mengapa? Karena Tauhid adalah ketaatan, ibadah, dan tawakal kepada Allah. Itu adalah perasaan bahwa seluruh alam semesta ini, dengan segala atomnya, menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala:
(Tidak ada sedikit pun urusan (itu) bagi kamu…) (QS Ali Imran: 128). Ridha dengan ketetapan Allah, percaya pada janji Allah, taat kepada Allah. Inilah Tauhid.
Padahal secara praktis, kita menyembah Zaid, ‘Amr, dan Bakr, atau kita menyembah diri kita sendiri…
Tauhid muncul pada seseorang seperti Ibrahim. Adakah orang yang, karena Allah mewahyukan kepadanya, ia bersedia menyembelih putranya? Kisah dan skenarionya mudah, tetapi penerapannya adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa:
(Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia (Ibrahim) membaringkan putranya di atas pelipis(nya), Kami panggil dia, “Wahai Ibrahim!”) (QS Ash-Shaffat: 103-104). Penyerahan diri (al-islam) telah terjadi, dan penyerahan diri inilah yang penting di sisi Allah Ta’ala. Itu berarti ego (al-ana) tidak ada di hadapan Allah, dan tidak ada apa pun kecuali Allah Yang Esa. Kita mungkin menemukan seseorang yang menerima penjara agar tidak jatuh dalam maksiat, tetapi menemukan seseorang yang mengatakan:
(…Penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka…) (QS Yusuf: 33), ini bukanlah hal yang mudah. (Ahabb – lebih aku sukai) ini adalah keadaan keimanan yang aktif, itu bukan penerimaan terhadap kenyataan yang sulit, tetapi cinta terhadapnya demi ketaatan kepada Allah.
Hari ini, banyak pertimbangan yang menguasai kita—seperti pertimbangan finansial, dan kedudukan—karena keadaan pengorbanan dan dedikasi yang ada bersama Allah mungkin telah menurun. Oleh karena itu, kita membutuhkan dorongan spiritual ini untuk memasuki tahap yang lebih baik, untuk merasakan perasaan keagamaan dengan lebih baik, alih-alih terpaku pada formalitas. Saya percaya bahwa fokus pada isu-isu moral pada tahap ini sangat penting, dan yang saya maksud adalah moralitas spiritual dan hubungan dengan Allah dalam segala maknanya—jauh dari beberapa kebingungan di kalangan sebagian orang di bidang ini juga—kita perlu mengembalikan keadaan spiritual ini dan kehadirannya, dan tidak terpaku pada Fikih dalam bentuknya yang umum hari ini, karena Fikih hanyalah sarana untuk mempersiapkan jiwa kita bagi turunnya nilai-nilai spiritual dan hubungan dengan Allah Tabaraka wa Ra’ala.
Catatan Kaki:
- Alquran al-Karim: Surah Al-Hajj (22), Ayat: 41, Halaman: 337.
- Alquran al-Karim: Surah Ali ‘Imran (3), Ayat: 110, Halaman: 64.
- Alquran al-Karim: Surah Thaha (20), Ayat: 132, Halaman: 321.
- Alquran al-Karim: Surah Ali ‘Imran (3), Ayat: 104, Halaman: 63.
- Alquran al-Karim: Surah Al-’Ashr (103), Ayat: 3, Halaman: 601.
- Alquran al-Karim: Surah Al-Ma’idah (5), Ayat: 105, Halaman: 125.
- Alquran al-Karim: Surah Al-An’am (6), Ayat: 164, Halaman: 150.
- Alquran al-Karim: Surah Al-Kahf (18), Ayat: 6, Halaman: 294.
- Alquran al-Karim: Surah Asy-Syu’ara (26), Ayat: 3, Halaman: 367.
- Alquran al-Karim: Surah Asy-Syu’ara (26), Ayat: 4, Halaman: 367.
- Alquran al-Karim: Surah Yunus (10), Ayat: 108, Halaman: 221.
- Alquran al-Karim: Surah An-Nisa (4), Ayat: 160, Halaman: 103.
- Alquran al-Karim: Surah Al-A’raf (7), Ayat: 163 – 165, Halaman: 171.
- Alquran al-Karim: Surah Al-A’raf (7), Ayat: 166, Halaman: 172.
- Alquran al-Karim: Surah Al-Ashr (103), dari awal Surah surah sampai Ayat ayat 3, Halaman: 601.
- Alquran al-Karim: Surah Thaha (20), Ayat: 14, Halaman: 313.
- Alquran al-Karim: Surah Al-Hajj (22), Ayat: 37, Halaman: 336.
- Alquran al-Karim: Surah Al-Ankabut (29), Ayat: 61, Halaman: 403.
- Alquran al-Karim: Surah Yunus (10), Ayat: 31 dan 32, Halaman: 212.
- Alquran al-Karim: Surah Ali ‘Imran (3), Ayat: 128, Halaman: 66.
- Alquran al-Karim: Surah Ash-Shaffat (37), Ayat: 103 dan 104, Halaman: 450.
- Alquran al-Karim: Surah Yusuf (12), Ayat: 33, Halaman: 239.
- Dua ceramah yang disampaikan di Universitas Az-Zahra, Iran, pada tanggal: 19 – 20 / 4 / 2013 M.
- Sumber: Situs Resmi Profesor Haidar Habballah hafidhahullah (semoga Allah menjaganya).