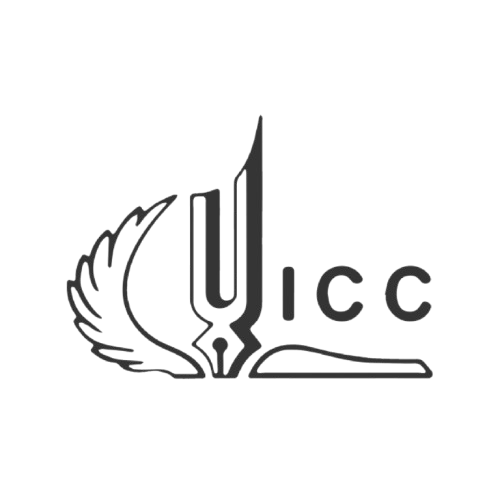Acara NGOBRAS (Ngobrolin Agama & Sains) Seri ke-4 yang diselenggarakan ICC Jakarta pada Jumat, 5 Desember 2025, menghadirkan diskusi mendalam mengenai relasi antara imajinasi manusia, akal imitasi (artificial intelligence), serta peran kesadaran manusia dalam proses penciptaan makna. Pada sesi ini, Haidar Bagir, dosen STAI Sadra, menjadi salah satu narasumber yang memaparkan perspektif filsafat Islam—khususnya pemikiran Ibnu Sina dan Mulla Sadra—untuk menjelaskan posisi manusia di tengah kecerdasan buatan yang semakin berkembang. Pemaparan beliau disampaikan secara sistematis dalam rangka menjawab pertanyaan pokok: dari mana sebenarnya keunggulan manusia berasal, dan apa yang tidak dapat ditiru oleh AI?
Dalam penjelasannya, Haidar Bagir memulai dengan menggambarkan persoalan dasar: selama ini, kesadaran manusia modern—disadari atau tidak—dibentuk oleh anggapan bahwa satu-satunya realitas adalah alam empiris dan satu-satunya daya yang valid adalah daya rasional yang menganalisis unsur-unsur empiris. Cara berpikir saintifik yang menempatkan rasio dan observasi empirik sebagai pusat kebenaran pada akhirnya membatasi manusia hanya pada level kemampuan analitis. Menurut beliau, jika manusia tetap bertahan pada mode itu, maka manusia akan kalah dari AI karena daya rasional-empiris sepenuhnya bersifat algoritmik—dan itu adalah wilayah yang justru menjadi keunggulan AI. AI tidak lupa, memproses jauh lebih cepat, dan sepenuhnya bekerja di wilayah analisis empirik.
Namun, manusia tidak hanya memiliki daya rasional-empiris. Dalam filsafat Ibnu Sina, manusia memiliki intuisi, yaitu kemampuan menyusun kesimpulan tanpa melalui proses silogisme yang bertahap, tanpa menyusun premis mayor dan premis minor. AI, kata beliau, akan selalu unggul dalam kerja logis-empiris, tetapi manusia memiliki kemampuan yang lebih tinggi: manusia memiliki daya imajinal. Dalam filsafat Islam, imajinasi bukan sekadar proses psikologis, tetapi merupakan alam sekaligus daya. Sebagai alam, ia adalah ruang wujud imajinal yang memiliki keberadaan; sebagai daya, ia adalah kemampuan jiwa untuk mengaksesnya. Bahkan dalam tradisi filsafat Yunani maupun filsafat Islam, wujud dalam alam spiritual mendahului wujud dalam alam empiris. Realitas turun dari tajalli Ilahi, baik vertikal maupun horizontal, hingga menjadi tiga alam ciptaan: alam ruhani, alam imajinal, dan alam empiris. Ketiganya tersusun bertingkat, dan manusia memiliki perangkat untuk mengakses ketiganya.
Dari perspektif ini, realitas empiris adalah lapisan paling bawah. Apa yang ada di alam empiris berasal dari alam imajinal, dan apa yang berada di alam imajinal berasal dari alam ruh. Adapun apa yang berada di alam ruh merupakan turunan dari Al-A‘yan ats-Tsabitah, yaitu entitas-entitas tetap dalam ilmu Tuhan yang menjadi asal dari seluruh wujud. Karena itu, imajinasi yang benar bukan sekadar khayalan kosong, tetapi dapat berupa penyaksian terhadap bentuk-bentuk hakiki. Contohnya adalah visi Nabi Muhammad saw dalam peristiwa Hudaibiyah, yang menggambarkan peristiwa yang akan terjadi—sebuah pengetahuan yang berasal dari alam imajinal yang benar.
Haidar Bagir menjelaskan bahwa alam khayal juga berfungsi sebagai wadah bagi bentuk-bentuk ruhani agar dapat dipahami manusia. Banyak gambaran wahyu mengenai sifat-sifat dan tajalli Allah Swt disampaikan melalui representasi imajinal; misalnya ungkapan metaforis tentang kedekatan hamba dengan Tuhan dalam peristiwa Mi‘raj—tentu bukan pada tataran zat, melainkan dalam bahasa imajinal yang dapat ditangkap manusia. Di sinilah peran sentral daya imajinasi: ia menjembatani alam empiris dan ruhani.
Beliau kemudian menjelaskan perbedaan bentuk daya imajinasi menurut filsafat Mulla Sadra. Dalam pandangan Sadrian, ada daya imajinasi yang terikat pada alam empiris dan ada yang terikat pada alam ruhani. Yang terikat empiris bekerja ketika manusia melihat objek: representasi masuk ke sensus communis, disatukan menjadi bentuk, lalu disimpan dalam memori untuk menghadirkan kembali wujud imaji. Daya ini juga memungkinkan penyusunan imaji baru dari dua konsep empiris, seperti kuda dan burung yang digabungkan menjadi kuda terbang. Meskipun tidak ada di alam empiris, ia tetap berada dalam domain imajinasi empiris.
Adapun daya imajinasi ruhani bersifat lebih tinggi: ia memberikan gambar bagi wujud ruhani agar dapat dipahami dalam bentuk imajinal. Misalnya imaji manusia tentang Allah Swt dalam pengalaman spiritual—bukan gambaran fisik, tetapi bentuk imajinal yang memiliki basis ruhani. Inilah wilayah yang sepenuhnya berada di luar jangkauan AI.
Menurut Haidar Bagir, AI hanya bekerja pada wilayah empiris-rasional. Ia tidak memiliki akses pada daya imajinal apalagi ruhani. Problemnya, sistem pendidikan modern tidak memberi ruang bagi pengembangan daya imajinasi tingkat tinggi ini. Maka AI tampak seperti mengalahkan manusia, padahal manusia belum menggunakan potensi penuhnya. Lalu apakah AI suatu saat dapat mencapai kapasitas tersebut? Di sinilah pentingnya konsep gerak substansial dari Mulla Sadra: yang bergerak secara substansial adalah jiwa. Manusia memiliki jiwa yang terus bergerak dan berkembang secara mandiri, sementara AI tidak punya jiwa dan tidak memiliki modus wujud. Yang ada pada AI hanyalah relasi: ia memproses data tetapi tidak memiliki keberadaan ruhani yang mandiri. Tanpa jiwa, AI tidak mungkin mengalami gerak substansial; karenanya ia akan selalu terikat pada alam empiris.
Beliau juga menyebut bahwa dalam psikologi transpersonal terdapat pengakuan akan kesadaran di luar kesadaran ego atau kesadaran dualistik. Manusia dapat berinteraksi dengan kesadaran tersebut melalui mimpi, pengalaman spiritual, atau intuisi prediktif yang tak bersumber dari pengalaman empiris. AI tidak mampu menjangkaunya karena AI tidak memiliki struktur kesadaran, tidak memiliki alam batin, dan tidak mengalami mimpi. AI hanya menampung input, sementara manusia memiliki pengalaman-pengalaman batin yang bersumber dari alam non-empiris.
Sebagai penutup, Haidar Bagir menegaskan bahwa AI bisa menjadi ancaman atau peluang, tergantung bagaimana manusia meresponsnya. Jika manusia tetap bertahan pada kesadaran empiris-rasional, manusia akan kalah. Namun jika manusia mengembangkan daya-daya luhur—khususnya daya imajinasi yang mampu mengakses alam imajinal dan ruhani—maka manusia akan tetap memiliki keunggulan yang tidak dapat ditiru AI. Karena itu, pendidikan harus diarahkan untuk membantu manusia mengenali dan mengembangkan dimensi-dimensi kesadaran yang lebih tinggi, sehingga AI menjadi alat, bukan pengganti manusia.