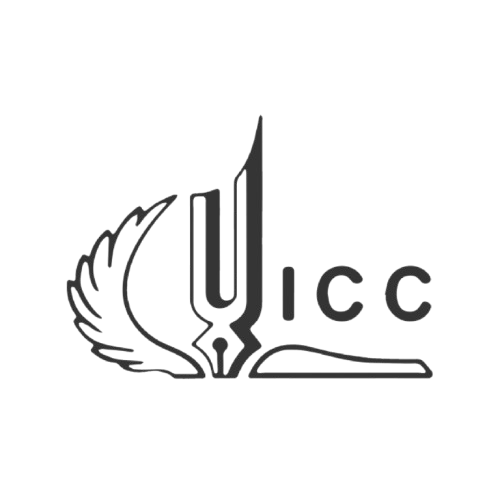Ahli filsafat dan mistisisme Islam asal Aljazair, Abdelazis Abbaci, memberikan pemaparan mendalam mengenai ontologi kepemimpinan dalam sesi seminar pendahuluan Seminar Internasional Nahjul Balaghah di Auditorium Imam Khomeini lantai 3, ICC Jakarta, pada Sabtu, 10 Januari 2026. Beliau membedah Surat Nomor 53 Nahjul Balaghah yang merupakan surat Imam Ali kepada Malik al-Asytar, yang dipandangnya sebagai sebuah statuta untuk kepemimpinan yang bisa dimanfaatkan oleh seorang pemimpin menuju keberhasilan. Beliau mengawali paparannya dengan membahas krisis kemanusiaan saat ini yang menurutnya bukan merupakan krisis sumber daya, melainkan krisis akhlak baik secara individu maupun sosial, terutama dalam ranah kepemimpinan. Secara spesifik, beliau menyoroti tindakan pemimpin dunia seperti Donald Trump atau Netanyahu sebagai bukti nyata krisis akhlak tersebut. Terpilihnya Donald Trump di Amerika Serikat dipandang sebagai pertanda adanya ketidakseimbangan aspek akhlak; di mana jika dianalisis, persoalan Trump bukan pada kecerdasannya, melainkan pada ketidakadilan di dalam dirinya sendiri. Potensi amarah, syahwat, dan akal dalam dirinya tidak seimbang sehingga terbentuk karakter manusia yang merusak alam. Hal inilah yang memicu pertanyaan malaikat mengenai manusia yang tidak adil pada dirinya sendiri sehingga termanifestasi negatif ke ranah publik, negara, dan masyarakat.
Beliau menjelaskan bahwa Nahjul Balaghah secara keseluruhan adalah kitab yang dapat dianggap sebagai tafsir Al-Qur’an dalam bentuk khutbah, surat, dan hikmah yang disampaikan secara detail serta sistematis oleh seorang manusia sempurna. Dalam masalah kepemimpinan, Surat 53 dinilai sangat membantu para pemimpin untuk memahami secara ontologis apa itu kepemimpinan, institusi, dan rakyat. Beliau mengkritik pemisahan antara keberadaan (being) dan apa yang harus dilakukan (doing) di zaman sekarang, di mana fakta diputus dari nilai. Kepemimpinan hari ini sering kali direduksi menjadi sekadar teknis pemerintahan dan manajemen risiko tanpa melihat apakah tujuan kepemimpinan tercapai secara eksistensial, bukan sekadar secara konseptual yang diambil dari ilmu politik atau pendidikan modern yang berasal dari filsafat empirik serta pragmatis. Beliau menegaskan bahwa Surat 53 sangat relevan untuk menyelesaikan masalah zaman ini dari sisi ontologis jika dibandingkan dengan konsep kepemimpinan yang hanya berasal dari pemikiran politisi atau filsuf tanpa mempertimbangkan aspek keberadaan.
Menggunakan salah satu prinsip Sadrian bahwa wujud adalah dasar segala sesuatu, beliau memaparkan bahwa kita bisa menilai pengaruh dan efek sesuatu pada eksistensinya, bukan pada konsep yang dipikirkan. Eksistensi jauh lebih luas dampaknya, bahkan ada wilayah eksistensi yang tidak bisa dicapai akal namun tetap berdampak terhadap kehidupan kita. Beliau mengkritik realitas yang dipahami sebatas material sehingga kebajikan dinilai hanya sebagai aksesori, bukan hal yang sifatnya eksistensial. Beliau membedakan hal ini dengan membedah akhlak menurut Immanuel Kant; jika bagi Kant kita lebih baik beragama daripada tidak (ketuhanan bersifat moral atas dasar kebutuhan), maka dalam Nahjul Balaghah akhlak ilahi bermanfaat tidak hanya pada kehidupan ini tapi juga kehidupan setelahnya. Tuhan di sini dipandang sebagai yang memengaruhi seluruh alam, bukan sekadar tuhan yang dipikirkan dalam situasi kehampaan psikologis. Beliau juga menyoroti rakyat yang hanya menjadi angka dalam politik modern, di mana suara mayoritas memunculkan orang seperti Donald Trump. Baginya, jumlah merupakan konsep buatan manusia yang tidak memenuhi syarat aturan yang disediakan oleh Allah SWT.
Melalui tesis Mulla Sadra yang menawarkan solusi dari filsafat wujud—yang perlu dibedakan dari eksistensialisme Barat yang menekankan manusia sebagai poros segalanya—beliau menjelaskan bahwa politik adalah manajemen wujud atau intensifikasi wujud. Politik menghadapi eksistensi yang bergradasi dari yang paling lemah seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan, hingga manusia sebagai satu kesatuan wujud dalam intensitas berbeda. Beliau menekankan bahwa jiwa sosial memiliki keberadaan real yang jika tidak dikelola dengan baik maka tidak akan mencapai kesempurnaan hakiki. Tauhid bukan hanya aspek individual namun juga sosial, di mana degradasi akan dialami secara kolektif jika keberhasilan hanya dirasakan terbatas oleh sedikit orang. Surat 53 membedah politik secara ontologis di mana Imam Ali memulai dari pembentukan hati, bukan desain institusi. Nasihat kepada Malik al-Asytar untuk mencintai masyarakat menuntut pemimpin mendidik diri sendiri agar memiliki keadilan internal, karena korupsi adalah penyimpangan dari keberadaan yang semestinya. Setelah itu, barulah seseorang memiliki kapasitas mengatur secara adil dengan melihat semuanya sebagai manifestasi Tuhan.
Di akhir paparannya, beliau mengingatkan bahwa institusi tanpa penyucian diri hanya menjadi prosedur tanpa ruh, karena pemimpin memengaruhi bentuk sosial melalui bentuk batinnya. Sesuai hadis, pemimpin yang adil bisa mengubah nasib masyarakat. Beliau juga membedakan epistemologi sebagai kasih sayang yang hanya bersifat konseptual dan merusak, dengan epistemologi yang sebenarnya yaitu makrifat, di mana manusia menjalani pengetahuannya agar bisa menjadi rahmat bagi yang lain. Beliau menyimpulkan bahwa humanisme yang dipromosikan adalah humanisme teosentris yang berporos pada tauhid, dan pemerintahan merupakan gerakan menuju tauhid di mana keberpihakan kepada kaum lemah menjadi ujian ontologis untuk mencapai kesejahteraan yang sifatnya ilahiah.