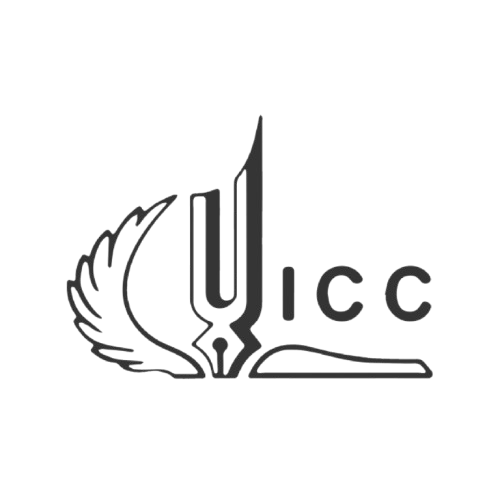Dogma hampir selalu datang dengan reputasi buruk. Ia kerap dipahami sebagai sesuatu yang menutup kemungkinan, membatasi kebebasan berpikir, dan mematikan kreativitas manusia. Dalam wacana modern, dogma sering disejajarkan dengan ketaatan buta—sebuah bentuk kepasrahan yang dianggap bertentangan dengan otonomi akal dan kebebasan individu. Akan tetapi, masalah utamanya bukan pada dogma itu sendiri, melainkan pada cara kita memahami kebebasan dan berpikir. Jika kebebasan hanya dimengerti sebagai ketiadaan komitmen dan berpikir hanya sebagai aktivitas rasional yang tak pernah berhenti meragukan, maka dogma memang akan selalu tampak mencurigakan. Namun, jika kebebasan dipahami secara eksistensial—sebagai keberanian untuk memilih dan menanggung makna—maka dogma tampil dalam wajah yang lain. Di titik inilah, dua suara dari tradisi yang berbeda—Imam Ali bin Abi Thalib dan Søren Kierkegaard—dapat dipertemukan, bukan untuk diseragamkan, melainkan untuk saling menerangi.
Bagi Kierkegaard, masalah terbesar manusia modern bukan kurangnya pengetahuan, melainkan kehilangan kesungguhan eksistensial. Manusia tahu banyak hal, tetapi tidak sungguh-sungguh hidup dari apa yang ia ketahui. Kebenaran direduksi menjadi sesuatu yang objektif dan netral, sementara hidup menuntut keterlibatan personal. Karena itu, Kierkegaard menolak gagasan bahwa iman adalah hasil kalkulasi rasional. Iman, baginya, adalah lompatan—keputusan eksistensial yang diambil dalam ketidakpastian. Justru karena tidak dapat dijamin sepenuhnya oleh akal, iman menuntut keberanian. Tanpa risiko, tidak ada iman; tanpa kegelisahan, tidak ada komitmen. Nada ini terasa sejalan dengan apa yang disampaikan Imam Ali, walau dalam bahasa yang berbeda. Dalam Nahj al-Balaghah, iman tidak pernah dibingkai sebagai kepemilikan intelektual, melainkan sebagai cara berada. Nilai manusia, kata beliau, tidak ditentukan oleh apa yang ia ucapkan atau klaimkan, tetapi oleh apa yang ia perjuangkan dan ia hidupi. Di sini, kebenaran tidak pernah netral; ia selalu menuntut sikap.
Kierkegaard sangat kritis terhadap iman yang diterima sebagai warisan sosial. Iman semacam ini, baginya, tidak eksistensial. Ia tidak mengguncang, tidak mengubah, dan tidak menuntut apa-apa. Ia hanya menjadi bagian dari identitas kolektif, bukan keputusan personal. Kritik ini menemukan resonansinya dalam tradisi Syi’ah. Imam Ali berkali-kali mengingatkan bahaya mengikuti kebenaran hanya karena figur, kelompok, atau kebiasaan semata. Dalam salah satu ucapannya yang terkenal, beliau berkata bahwa kebenaran tidak diukur dari manusia, melainkan kenalilah kebenaran, maka engkau akan mengenal para pengikutnya. Kutipan ini mengandung pesan eksistensial yang tajam karena memindahkan tanggung jawab dari komunitas ke individu. Dogma, dalam cahaya ini, bukan sesuatu yang hidup dengan sendirinya. Ia baru menjadi bermakna ketika dipilih secara sadar setelah melalui pertanyaan dan kegelisahan. Tanpa pilihan, dogma memang membeku. Dengan pilihan, ia menjadi poros keberadaan.
Baik Kierkegaard maupun Imam Ali tidak menolak akal. Yang mereka kritik adalah kesombongan akal—keyakinan bahwa segala sesuatu bisa dituntaskan oleh konsep. Kierkegaard menyadari bahwa ada pengalaman-pengalaman dasar manusia, seperti penderitaan, kecemasan, dan kematian, yang tidak bisa diselesaikan oleh logika. Iman hadir bukan untuk menjawab semua pertanyaan, melainkan untuk menopang manusia ketika pertanyaan tidak lagi memberi pegangan. Imam Ali mengekspresikan kesadaran ini dengan bahasa tauhid yang hening bahwa kesempurnaan tauhid adalah meniadakan sangkaan-sangkaan tentang-Nya. Ini bukan ajakan untuk berhenti berpikir, melainkan pengakuan akan batas berpikir. Ada wilayah di mana akal harus belajar diam. Dogma menandai wilayah itu—bukan sebagai larangan, tetapi sebagai perlindungan agar manusia tidak terjebak dalam ilusi penguasaan total atas realitas. Dalam perspektif ini, dogma tidak membunuh kebebasan berpikir; ia justru menyelamatkan manusia dari tirani pikirannya sendiri.
Filsafat eksistensial selalu bertanya: apakah aku hidup secara autentik? Pertanyaan ini relevan juga bagi dogma. Menariknya, baik menerima dogma maupun menolaknya bisa sama-sama tidak autentik jika dilakukan tanpa kesadaran. Seseorang bisa menolak dogma hanya karena mengikuti arus zamannya, sebagaimana seseorang bisa menerimanya hanya karena tradisi. Keduanya sama-sama hidup dalam apa yang Kierkegaard sebut sebagai kerumunan—kehidupan yang tidak sungguh-sungguh dipilih. Imam Ali menyebut keadaan ini sebagai kelalaian (ghaflah). Manusia hidup, tetapi tidak hadir sepenuhnya dalam hidupnya sendiri. Dogma menjadi eksistensial ketika ia tidak lagi menjadi milik “kami”, tetapi menjadi keputusan “aku” di hadapan Yang Mutlak. Pada titik ini, dogma bukan lagi penopang identitas sosial, melainkan beban tanggung jawab personal.
Eksistensialisme modern sering memaknai kebebasan sebagai ketiadaan ikatan. Namun, baik Kierkegaard maupun Imam Ali menunjuk pada kebebasan yang lebih dalam: kebebasan untuk mengikat diri secara sadar. Imam Ali mengungkapkan ini dengan sangat jernih dalam doanya yang terkenal bahwa beliau tidak menyembah Tuhan karena takut neraka atau mengharap surga, tetapi karena mendapati Tuhan layak untuk disembah. Ini adalah bahasa eksistensial yang murni. Iman di sini bukan kalkulasi untung-rugi, bukan kepatuhan mekanis, melainkan keputusan terdalam tentang makna hidup. Dogma tidak hadir sebagai paksaan eksternal, melainkan sebagai orientasi batin yang dipilih dengan penuh kesadaran. Di titik ini, kebebasan dan dogma tidak lagi saling berlawanan. Justru kebebasan menemukan kedalamannya ketika ia berani berkomitmen.
Mungkin masalah terbesar kita dengan dogma bukan bahwa ia mengekang, melainkan bahwa ia menuntut terlalu banyak. Dogma menuntut konsistensi, keberanian, dan kesediaan untuk menanggung konsekuensi dari apa yang kita yakini. Tuntutan semacam ini memang tidak pernah nyaman. Imam Ali dan Kierkegaard, masing-masing dengan caranya, mengingatkan bahwa hidup selalu menuntut pilihan terakhir. Tidak memilih pun adalah sebuah pilihan. Dan setiap pilihan terakhir—disadari atau tidak—selalu bersifat dogmatis dalam arti eksistensial. Pertanyaannya bukan apakah kita hidup dengan dogma, melainkan dogma mana yang kita pilih, dan apakah kita cukup jujur untuk hidup setia padanya. Di sanalah dogma berhenti menjadi konsep dan mulai menjadi jalan.